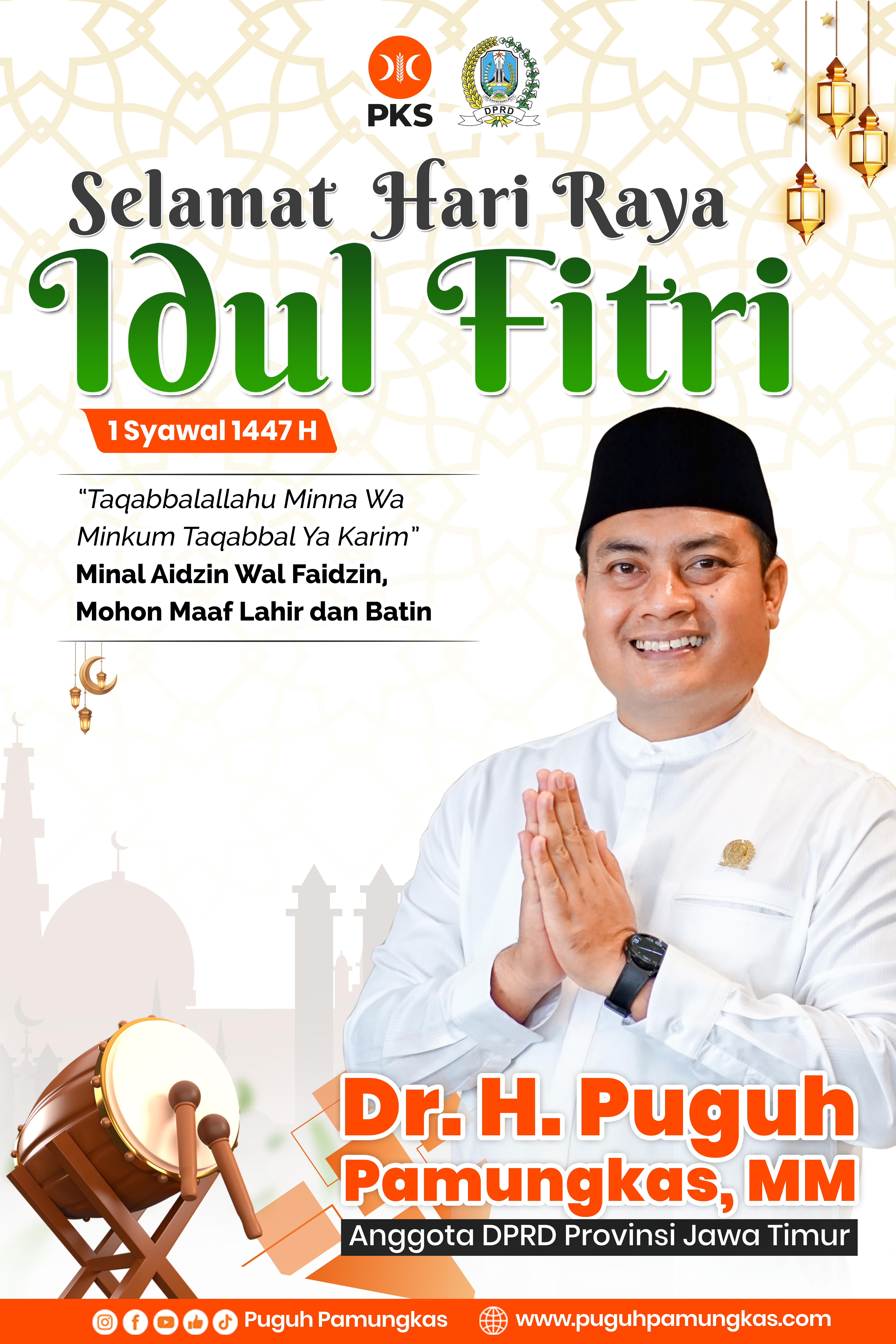Oleh : H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA)
“Akhirnya bisa dimulai,” begitu ujar Horst Koeler, Presiden Jerman, pada acara pembukaan Piala Dunia 2006 di Muenchen waktu itu (Kompas, 10/6/2006 ). Tepukan gemuruh pun waktu itu muncul dari 66.000 penonton di stadion menyambut turnamen olah raga dengan kulit bundar–yang menurut buku The World’s Game: A History of Soccer karya Bill Muray sudah dimainkan sejak awal masehi—ini sebagai peristiwa olah raga terbesar. Ya, even yang sejak tahun 1930 digelar empat tahun sekali itu, harus dibilang sebagai terbesar di planet bumi ini. Mengapa? Setiap even digelar milyaran pasang mata manusia di seluruh penjuru dunia nyaris tidak dapat dibendung untuk menontonnya. Fantastis bukan? Kepopuleran olah raga yang menggunakan 11 pemain ini bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sudah tampak sejak dulu. Mungkin itulah sebabnya mengapa pada tahun 1920 Jules Rimet, si Presiden FIFA –yaitu sebuah oraganisasi resmi sepak bola internasional–waktu itu, mengusulkan agar pertandingan sepak bola ini dijadikan sebagai turnamen yang terpisah dengan olimpiade. Meskipun agak lama akhirnya usul tersebut goal juga ketika pesta olah raga–yang pernah dilarang oleh Raja Edward III dari Inggris dan Raja James I dari Skotlandia–ini digelar untuk pertama kalinya pada tahun 1930 di Uruguay. Pada turnamen yang digelar oleh organisasi yang didirikan 21 Mei 1904, ini si tuan rumah berhasil keluar sebagai kampiunnya. Gelar tersebut sekaligus sebagai hadiah ulang tahun ke-100 kemerdekaan negara tersebut.
Selanjutnya, even empat tahunan yang digelar secara resmi oleh FIFA tersebut, memang telah menjelma menjadi industri hiburan global sebagaimana yang kita kenal sekarang. Revolusi bidang teknologi informasi membuat dampak dari perhelatan sepak bola bukan hanya lebih mondial tetapi sajiannya juga lebih menghibur. Dampak yang diakibatkan penyelengaraannya tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga berdampak sosial, politik, dan ekonomi. Simak saja kehidupan para bintangnya. Kebintangan di dunia persepakbolaan telah menempatkan mereka setara dengan para tokoh kelas dunia. Orang-orang Inggris saja heran dan kadang tidak bisa menjawab, mengapa gaji seorang pemain bintang sepak bola bisa lebih tinggi dari gaji seorang perdana menteri. Sebagai contoh bintang Inggris Wayne Rooney yang awal mula jaya masih berusia 20 tahun itu mampu mengumpulkan kekayaan kebih dari 30 juta poundsterling atau sekitar 450 miliar. Sebuah kekayaan yang tidak mungkin bisa dikumpulkan oleh seorang PNS Indonesia golongan IV/e sekalipun jika, maaf, tidak mau korupsi. Nama-nama seperti Geoge Weah (Liberia, yang belakangan menjadi Presiden ke-25 negara tersebut) , Ruud Gullit (Belanda), Ronaldo (Brasil), Christiano Ronaldo (Portugal), Leonel Messi (Argentina) dan sederet megabintang sepak bola lainnya adalah contoh orang-orang yang hidup bergelimang uang dari sepak bola.
Kejuaraan cabang olah raga, yang memperebutkan Piala Jules Rimet karya Abel Lafleur sang pematung Perancis, ini juga telah menjadi ikon budaya abad 20-21. Olah raga–yang menurut buku Sepak Bola (2019) karya Ina Hasanah pertama kali dimainkan di Cina oleh para tentara untuk melatih fisik sekitar–ini juga telah menjadi bagian simbolisme kebanggaan heroik bangsa di ranah global. Kehadirannya telah membuat hampir setiap orang tergila-gila dalam ilusi imajiner yang juga dengan cara yang gila-gilaan, seolah-olah semuanya nyata adanya. Tidak terkecuali kita tentunya.
Dalam konteks ini kita memang tidak akan mempersoalkan bagaimana Trinidad dan Tobago–gegara bola sebuah negara kecil yang terletak antara Amerika Utara dan Amerika Selatan dan hanya berpenduduk 1,3 juta jiwa–itu suatu ketika menjadi terkenal ke seantero dunia ketika bisa tampil di piala dunia tahun 2006 itu. Kita hanya menyoroti atau lebih tepat meratapi diri kita. Mengapa kita, yang sedari dulu mengkalaim sebagai negara yang paling dalam hal kekayaan alam, ini sampai sekarang hanya bisa berderajat sebagai penonton. Simbol-simbol kebanggan seperti Indonesia Raya, Pancasila Sakti, Indonesia yang kaya raya tidak pernah tampak nyata dalam even bernama sepak bola atau bahkan untuk sebagian besar cabang olah raga lainnya. Setiap empat tahun sekali kita hanya punya kebanggaan nonton bareng. Ketika suatu ketika siaran langsung diblokir, kita hanya kuasa menyisihkan sebagian uang kita untuk membeli alat penangkap siaran, dan semua jenis penunjang untuk sebuah kegiaatan yang bernama “nonton bola”.
Menjadi penontonpun kita mungkin belum tergolong penonton yang baik. Simak saja perilaku sejumlah bonek ( bondo nekat ) ketika tim dukungannya usai bertanding, baik menang apalagi kalah. Jika menang merayakannya dengan cara yang gila tetapi ketika kalah pun mengamuk dengan cara yang gila pula. Jadi, gegara sepak bola, bisa membuat penikmatnya “gila-gilaan”. Setiap usai pertandingan dulu selalu saja kita baca berita pembakaran kendaraan, amuk masa di jalan, adu otot antar suporter, dan sejumlah peristiwa anarkhis lainnya. Tidak jarang peristiwa tersebut di samping menelan korban harta juga nyawa. Untuk yang terakhir ini, malah tidak hanya melibatkan antar suporter, pamain bintang pun bisa menjadi sasaran amuk oleh pendukungnya sendiri. Kita tentu masih ingat tentunya ketika Andreas Escobar, back kesebelasan Kolumbia ini, harus meregang nyawa oleh pendukungnya sendiri akibat dianggap berdosa atas gol bunuh diri yang ia buat secara tidak sengaja.
Sekalipun peristiwa seperti itu memang menunjukkan, bahwa perilaku ‘gila’ bukan monopoli penonton Indonesia. Akan tetapi, untuk sebuah negara yang tidak pernah menjadi juara dunia seperti kita rasanya memang ironis. Mengapa ? Akibat yang ditimbulkan dengan sebuah kegiatan nonton bola sering harus dibayar mahal tidak saja oleh yang terlibat langsung tetapi juga masyarakat lain yang tidak berdosa.
Kini kita sedang berada di dua perhelatan prestisius sepak bola berskala internasiol: Piala Eropa ( Euro 2021) dan Piala Amerika ( Copa America).
Di Copa Amerika, 2 negara raksasa sepak bola, Brasil dan Argentina, yang berhasil menuju grandfinal. Sedangkan, di Piala Eropa (Euro 2021) juga telah mendapatkan dua negara raksasa bola menuju grandfinal, yaitu Inggris dan Italia. Negeri Samba Brasil berhasil menuju final setelah menang tipis 1-0 atas Peru, sedangkan Argentina berhasil menuju puncak setelah drama adu penalti yang berakhir dengan skor 3-2 melawan Kolumbia. Inggris berhasil menuju partai puncak setelah menekuk Denmark 2-1, sedangkan Italia menuju puncak setelah berhasil menenggelamkan ambisi raksasa sepak bola Spanyol juga setelah drama adu pinalti yang berakhir dengan skor 4-2.
Keempat tim nasioanal dari 2 benua itu memang layak memperebutkan lambang supremasi sepak bola dari benua masing-masing. Akan tetapi, tim negara mana yang berhasil sulit diprediksi. Setiap tim punya kelebihan di samping kekurangan masing-masing. Faktor kepiawaian pelatih, skill pemain ( teknik ), dan stamina pemain sering menjadi penentu keberhasilan tim. Di samping itu faktor keberuntungan juga tidak boleh diabaikan. Betapa sering kita saksikan suatu tim tangguh secara kasat mata, dapat tumbang oleh tim beberapa level di bawahnya.
Akan tetapi, ada faktor lain yang sekalipun tidak diperhitungkan ikut mempengaruhi keberhasilan tim. Faktor itu ialah eksistensi para petualang bola yang sebenarnya tidak menikmati sepak bola tetapi bisa mengambil keuntungannya. Para petualang itu adalah para spekulan (judi). Mereka sering bermain di balik layar dengan operasi yang sering sulit dapat dilihat oleh orang kebanyakan. Sasaran mereka adalah pemain, wasit, atau penyelengara. Sebagai contoh, tim sekelas Juventus pernah didegradasi akibat hukuman atas kesalahannya terlibat pengaturan skor.
Ironisnya, para petualang bola itu tampaknya sudah masuk ke masyarakat hampir semua level. Modusnya sebenarnya kurang lebih sama, yaitu menjagoi sebuah tim dengan cara taruhan. Bagi masyarakat awam, pada mulanya memang dimulai dari yang kecil-kecilan seperti mentraktir bakso atau membelikan sebungkus rokok. Tapi ketika ilusi sudah mulai terbangun, tanpa terasa sedikit demi sedikit omset taruhan pun semaikin besar pula. Tak urung, kebiasaan seperti itu sampai menimbulkan jargon “ kaya mendadak dan miskin mendadak”. Sebagai ilustrasi ada pasangan yang bercerai gara-gara perhelatan sepak bola. Sang istri sangat kecewa dan marah besar kepada suaminya. Pasalnya, seekor sapi kesayangan keluarga tiba-tiba raib, karena diambil orang.
Belakangan diketahui bahwa seekor yang menjadi kekayaan satu-satunya itu, telah dipertaruhkan oleh sang suami dengan orang ketika sama-sama nonton sebuah babak final sepak bola berlangsung. Pada hal, semua orang kampung tahu dia adalah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Akibat nonton sepak bola juga sering membuat jadwal kegiatan harian berubah. Penyelenggaraan sepak bola yang berada di benua lain, karena perbedaan letak geografis, menyebabkan jam tayangnya harus terjadi pada waktu istirahat. Bagi yang sudah sangat kecanduan pukul berapa pun ditayangkan, bukanlah persoalan. Kegiatan berupa “harus menonton’ itu sering mempengaruhi jadwal rutin wajib sebelumnya. Betapa sering kita saksikan seorang pegawai (PNS atau pegawai swasta) mengantuk, terlambat, bahkan tidak masuk kantor gegara begadang sampai pagi di hadapan televisi karena harus menyaksikan aksi Leonel Mesi dan Neymar. Pada saat demikan kinerjanya jelas terganggu. Bagaimana kalau hal demikian menimpa buruh bangunan atau buruh tani harian? Akhirnya, kesimpulan kita hanya satu kalimat:”Nonton sepak bola dapat menurunkan produktivitas.”
Kalau sudah demikian ada baiknya, setiap ada perhelatan sepak bola prestisius, kita bertanya kepada hati kita, “bola atau nasi?” Pertanyaan simbolik ini perlu kita ajukan agar kita tidak terbiasa mengalahkan primer dari yang sekunder, mendahulukan yang mubah dengan mengalahkan yang wajib. Menonton bola adalah masalah sekunder dan mubah saja, sedangkan bekerja adalah masalah primer nan wajib. Selamat menikmati grand final, tetapi jangan lupa dengan yang lebih penting!
Lumajang, Juli 2021