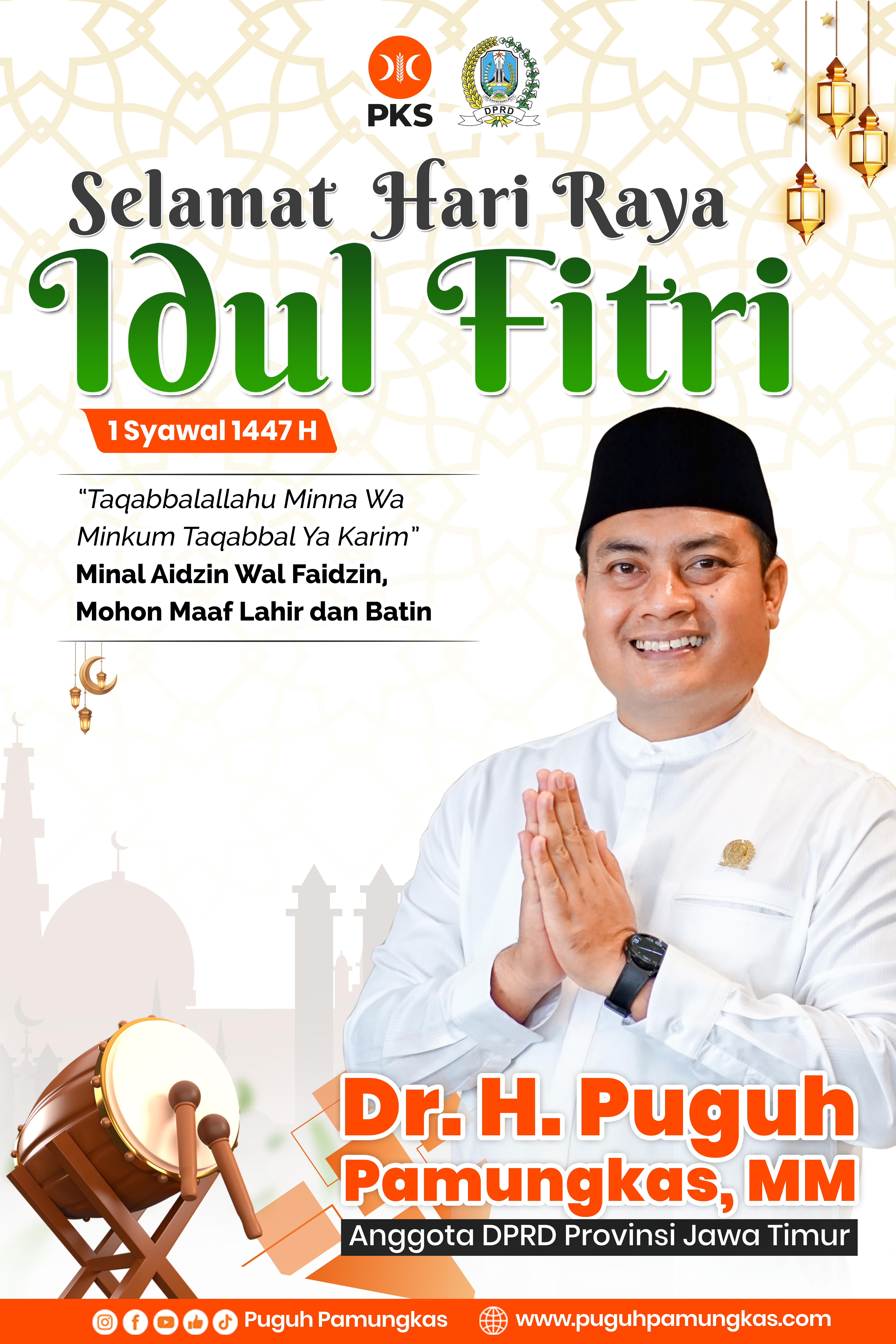Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim PTA Banjarmasin)
Jakarta, beritalima.com | Sejak kecil, kita diajarkan tentang adab. Jabat tangan sambil mencium tangan orang tua, mengucap permisi ketika lewat, tidak mengambil barang orang lain, hingga otomatis berkata “terima kasih” ketika menerima sesuatu. Itu semua bukan sekadar ritual, melainkan bagian dari pendidikan moral yang diwariskan keluarga agar kita tumbuh menjadi pribadi yang tahu batas, menghargai orang lain, dan tidak serakah.
Namun, seiring bertambahnya usia, nilai-nilai luhur itu kerap hilang ditelan ambisi. Anak yang dulunya sopan berubah menjadi remaja keras kepala. Anak yang dulu tahu arti “jangan ambil milik orang lain” kini, ketika dewasa, menjadi pelaku korupsi yang merampas hak rakyat. Para pejabat yang kini terseret kasus hukum sesungguhnya pernah melalui fase pengenalan moral yang sama. Mereka pasti pernah ditegur orang tuanya: “kalau dikasih, bilang apa?”—tetapi di kemudian hari justru lupa mengucap terima kasih kepada rakyat yang memberi mereka amanah.
Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah orang tua gagal mendidik? Ataukah sistem sosial politik kita yang mencabut akar nilai-nilai itu dari hati manusia?
Masalahnya bukan sekadar pada individu, melainkan pada ekosistem yang gagal merawat nilai-nilai dasar. Di dunia politik, yang lebih dihargai seringkali bukanlah kejujuran atau adab, melainkan kelicikan, kelihaian mengakali aturan, dan kemampuan menjaga citra. Sementara di ruang sosial yang lebih luas, masyarakat pun terbiasa memaafkan bahkan menormalisasi perilaku buruk pejabat. Koruptor tetap dielu-elukan, pelanggar hukum masih mendapat tempat terhormat. Nilai adab yang ditanamkan sejak kecil kalah oleh budaya permisif dan sistem yang busuk.
Carut-marut politik hari ini adalah cermin kegagalan kolektif. Kita, sebagai bangsa, telah membiarkan nilai “terima kasih” berganti dengan “transaksi.” Nilai “permisi” berganti dengan “sikut kanan-kiri.” Nilai “jangan ambil milik orang lain” berganti dengan “asal pintar menyembunyikan jejak.”
Jika sejak kecil kita sudah diajari adab, maka seharusnya kedewasaan politik kita berangkat dari fondasi itu. Tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, maka kita sedang hidup di zaman di mana adab berhenti di rumah, tidak pernah ikut masuk ke ruang kekuasaan.
Mungkin sudah saatnya kita merenungkan kembali: bagaimana caranya agar nilai-nilai sederhana masa kecil tidak berhenti sebagai kenangan manis, tetapi benar-benar menjadi landasan moral dalam mengelola negara? Karena tanpa itu, bangsa ini hanya akan terus melahirkan generasi yang fasih berkata “terima kasih” di rumah, tetapi rakus merampas di kantor kekuasaan.