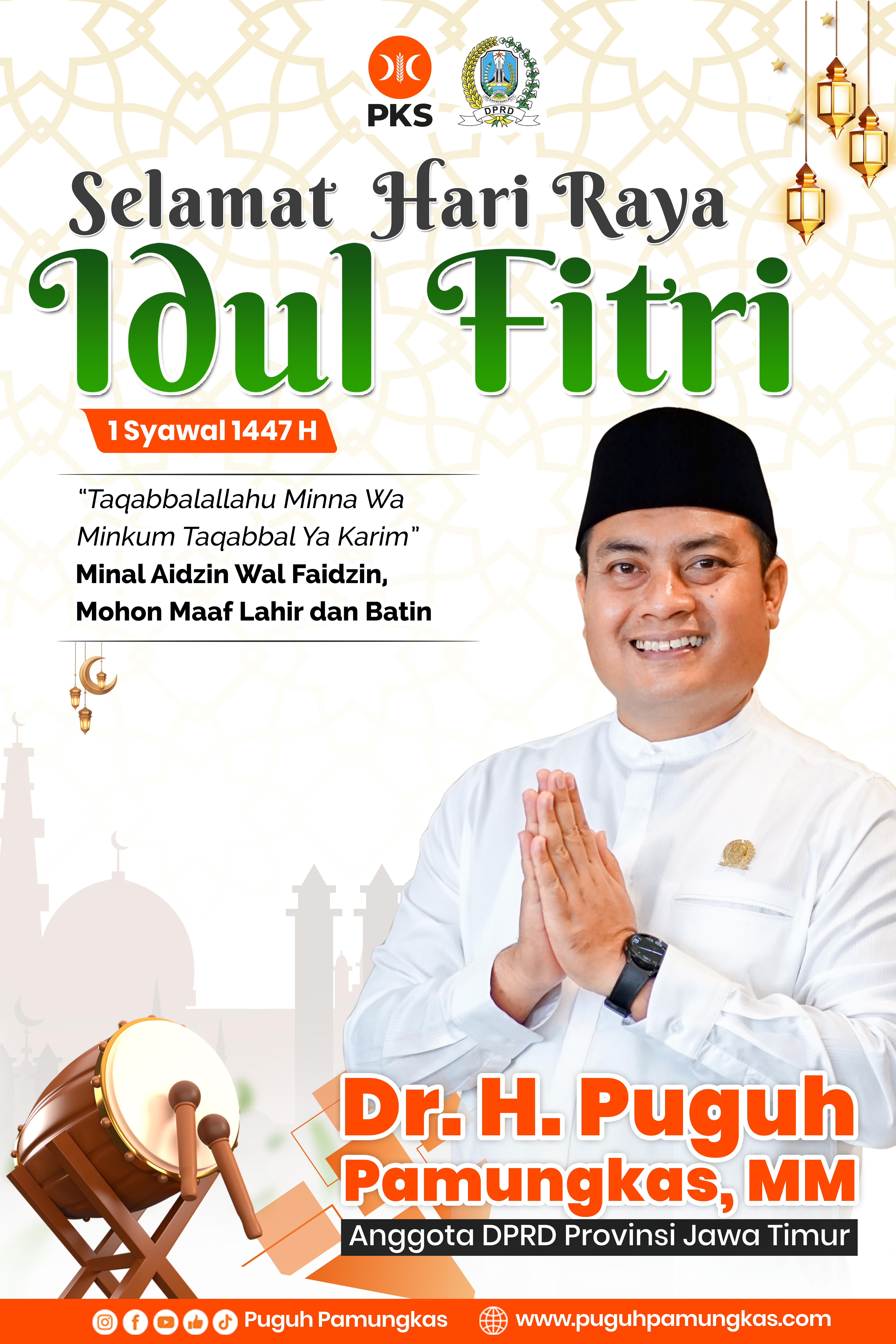Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim PTA Banjarmasin)
Opini, beritalima.com | Ada dua predikat tentang negeri ini yang selalu melekat di benak saya sejak kecil: Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Dua label itu dulu menjadi kebanggaan yang sering diulang dalam buku pelajaran dan pidato para pejabat. Dan memang, sebagai negara maritim, fakta itu tak terbantahkan. Lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, dan itu tidak akan pernah berubah.
Namun, hal yang sama tampaknya tidak bisa lagi dikatakan tentang predikat kita sebagai negara agraris. Seiring waktu, istilah itu mulai terdengar seperti kenangan—indah tentang masa lalu untuk dikenang, tetapi kini semakin jauh dari kenyataan. Lahan pertanian yang dulu kita banggakan itu kini semakin sempit. Sawah-sawah subur dan hamparan padi kuning nan luas saat menjelang panin, kini berubah menjadi kompleks perumahan, pabrik, atau kawasan industri. Ironisnya, semua itu sering dibungkus dengan kata “pembangunan”.
Kita tentu tidak bisa menolak pembangunan. Peningkatan kebutuhan lahan untuk infrastruktur, perumahan, dan industri adalah keniscayaan dari bertambahnya jumlah penduduk. Namun, yang menjadi persoalan adalah cara kita memilih dan memanfaatkan lahan. Pembangunan sering dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan nilai strategis tanah pertanian. Lahan subur yang dulu menumbuhkan padi kini tertutup beton dan aspal. Alam yang dulu sejuk kini berubah menjadi pengap dan panas.
Padahal, dalam logika kebijakan yang sehat, lahan produktif pertanian seharusnya menjadi kawasan yang dilindungi. Industrialisasi dan ekspansi ekonomi mestinya diarahkan ke lahan yang tidak produktif secara agraris. Namun, dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya: lahan subur menjadi rebutan karena dianggap strategis dan bernilai jual tinggi. Pemilik tanah pun tergoda untuk menjualnya, bukan karena serakah, tetapi karena keadaan.
Kebijakan pertanian yang tidak berpihak dan kesejahteraan petani yang stagnan membuat bertani terasa seperti pilihan yang melelahkan. Menggarap sawah membutuhkan biaya besar dan tenaga banyak, sementara hasilnya tak seberapa dan penuh ketidakpastian. Tak heran jika banyak petani merasa lebih “aman” menjual lahannya kepada investor dan menyimpan uangnya di bank. Lahan yang dulu menjadi sumber kehidupan kini justru dijual demi bertahan hidup.
Inilah paradoks yang mencemaskan: kita membanggakan diri sebagai negara agraris, tetapi kehilangan petani setiap hari. Kita memuja pembangunan, tetapi mengorbankan sumber pangan kita sendiri. Ketika sawah berganti beton, bukan hanya lahan yang hilang, melainkan juga kearifan, tradisi, dan identitas bangsa yang sejak lama tumbuh di atas tanah-tanah subur itu.
Sudah saatnya pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya gedung dan jalan, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga keseimbangan dengan alam dan keberlanjutan pangan. Negeri agraris sejati bukanlah yang memiliki banyak sawah di masa lalu, melainkan yang tetap menjaga tanahnya untuk memberi kehidupan bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, semua kebijakan yang menopang kepada kejayaan negara agraris patut mendapat perhatian sekaligus prioritas.