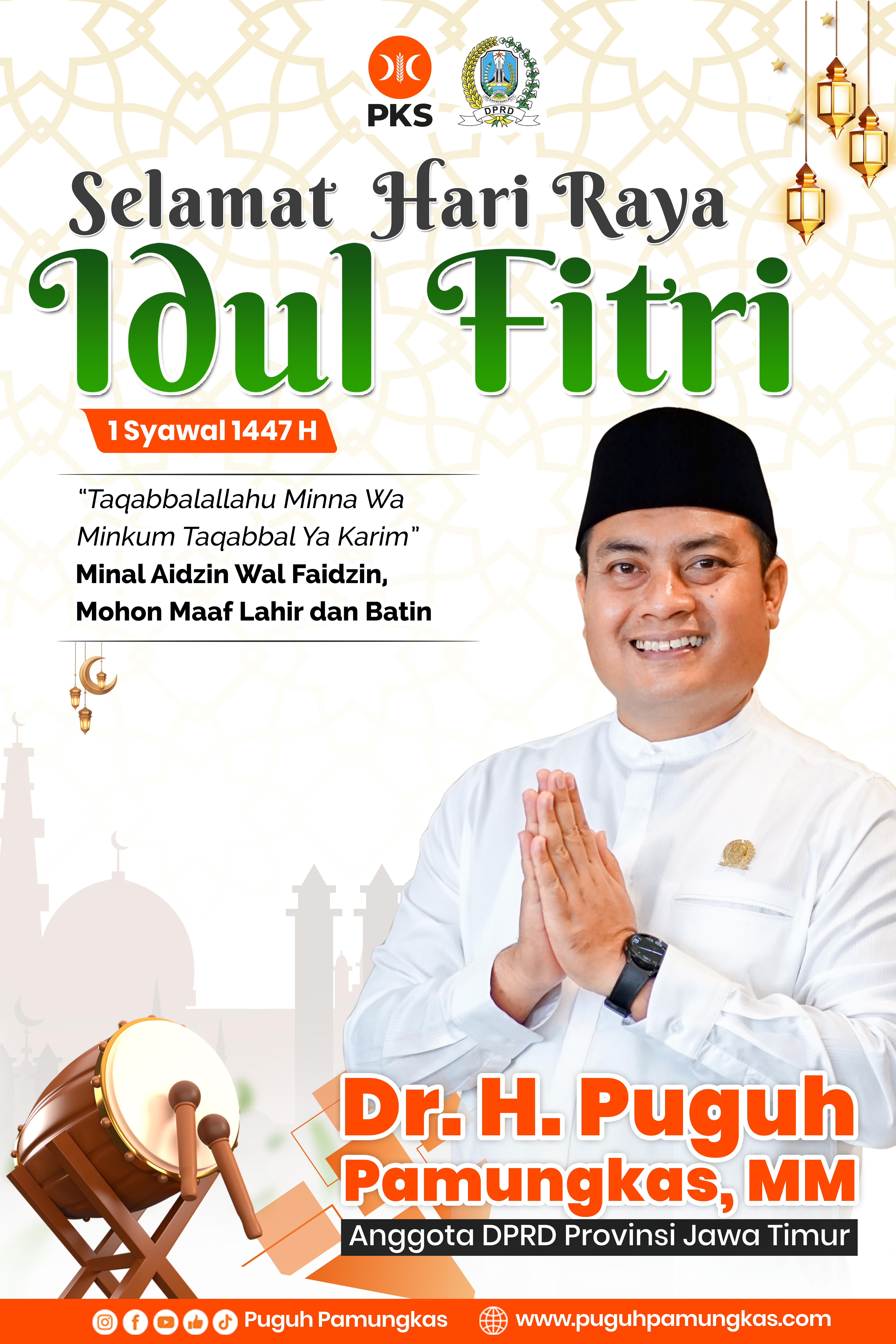Oleh : H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Masih terngiang di telinga saya gumaman seorang teman sebut saja Bokir (bukan nama sebenarnya) kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saat itu, rupanya ia sangat tersinggung ketika dalam suatu “kerja bakti” di kantor, salah seorang teman menunjuk sesuatu dengan kaki disertai perintah yang dialamatkan kepada Bokir. Dengan tanpa beban apa pun, teman tadi kemudian berlalu. Rupanya sikap teman tadi membuat Bokir sangat tersinggung. Dengan penuh kesal dia bergumam sendirian “Kalau di suku saya, berani menunjuk dengan kaki sambil memerintah begitu, sudah hilang kakinya,” gumamnya. Dengan gumaman demkian rupanya ia ingin memberitahukan kepada saya bahwa menurut etika (tata krama) di daerahnya, menunjuk sesuatu dengan kaki merupakan salah satu perbuatan yang dapat membuat orang sangat tersinggung karena dianggap merendahkan harga diri.
Mendengar gumamam Bokir tersebut saya memang sedikit terperanjat. Saya pun segera sadar dan teringat sebuah negara besar bernama Indonesia, negara kita semua. Sebagai sebuah negara kepulauan Indonesia memang memiliki ribuan pulau dan suku bangsa. Negara paling luas se-Asia Tenggara dan urutan ke-15 terluas di dunia ini, sebagaimana ditulis dalam situs laman indonesiabaik.id, menurut catatan pemerintah, pada tahun 2021 memiliki jumlah pulau hingga 17.000 pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar di barbagai wilayah provinsi. Tercatat ada 5 Provinsi dengan jumlah pulau terbanyak, yaitu: Papua Barat (4.514 pulau), Kepulauan Riau (2.025 pulau), Sulawesi Tengah (1.572 pulau), Maluku (1.337 pulau), Maluku Utara (837 pulau). Dari ribuan pulau tersebut ternyata juga dihuni berbagai suku. Dikutip dari laman Indonesia.go.id, Selasa (31/1/2023), Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air berdasarkan data sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa sendiri merupakan kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi.
Dari berbagai suku tersebut tentu juga wajar jika mereka mempunyai ragam budaya dan adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan budaya tersebut kadang sangat ekstrim. Dari contoh anekdot di atas tampak jelas, bahwa ukuran tabu dan bukan tabu juga sering berbeda. Apa yang boleh di suatu suku tertentu belum tentu boleh bagi suku yang lain. Perbedaan nilai budaya itu mengharuskan kita mengenali dan kemudian menghormati. Oleh sebab itu benar kata pepatah bijak “Di mana bumi dipijak, langit dijunjung.” Pepatah ini mengajarkan kepada kita, bahwa menghormati adat istiadat di mana kita berada ‘wajib’ hukumnya. Mengenali bahasa setempat juga sangat perlu. Tujuannya, antara lain agar jangan sampai kita mengucapkan suatu kata atau bahkan menyusun kalimat dengan sebuah diksi yang sangat membuat orang setempat sangat tersinggung, bahkan marah. Kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu pernah terjadi demo besar bernuansa rasial akibat sebuah ucapan yang menyinggung suku tertentu.
Dalam praktik, apa yang ditunjukkan para elite kita tampaknya sering paradoks dengan harapan ideal tersebut. Betapa kita saksikan para tokoh elit kita ( politisi dan akademisi) sering mencontohkan retorika murahan di ruang publik. Mereka dengan tanpa beban, sering memakai diksi-diksi kasar kepada lawan bicara. Ucapan saling saling olok di ruang publik tersebut dengan tanpa sadar telah mereka pertontonkan kepada rakyat. Mereka juga tidak sadar, bahwa kata-kata kasar tersebut sering dipotong dan karena dianggap ‘menarik’ lantas di sebar di berbagai medsos, sehingga menjadi viral. Generasi muda pun kemudian ikut ‘menikmatinya’. Karena dianggap sudah biasa, akhirnya diksi-diksi kasar tersebut seolah menjadi tradisi yang biasa-biasa saja meskipun dengan akibat yang belum tentu biasa.
Fenomena tersebut rupanya menjadi salah satu yang disayangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2023 lalu. Bahkan dalam konteks ini beliau sampai menyebut “telah terjadi polusi di ruang budaya kita”. Kebiasaan sebagian intelektual mengucapkan kata-kata kasar berisi makian, baik kepada personal maupun institusi terhormat tertentu, dianggap telah mencederai nilai-nalai kesantunan yang diajarkan para leluhur. Ironisnya, polusi ini rupanya justru diciptakan oleh para elite dan secara tidak sadar sekaligus mengajarkannya kepada generasi muda. Beliau tentu sadar, bahwa budaya tidak santun tersebut bisa menghinggapi generasi muda dan berpotensi memancing orang lain marah. Dalam konteks Indonesia yang multi etnis, jika kebiasaan seperti itu terus dibiasakan tentu akan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aneka suku bangsa yang semula menjadi aset bangsa, akan berubah menjadi momok menakutkan karena jika tidak disadari oleh semua pihak akan berpotensi menimbukkan disintegrasi bangsa. Bhineka Tunggal Ika juga akan menjadi sekedar jargon belaka. Dunia Perguruan Tinggi beserta segenap insan di dalamnya, sebagai basis intektual yang nota bene kelompok manusia terdidik, tentu punya tanggung jawab moral terhadap hal ini. Bukan malah sebaliknya, justru menjadi penyokong utama bagi benih-benih disintegrasi bangsa.
Tanggung jawab moral para intelektual (termasuk para budayawan) memprtahankan keutuhan NKRI, harus sepadan dengan tanggungjawabnya melakukan pengawasan kepada jalannya pemerintahan, siapa pun rejimnya. Dengan tanpa harus memaksakan kehendak, kritik konstuktif memang perlu terus disuarakan sebagai tanggung jawab akademis. Pada saat yang sama, juga tetap harus disadari, bahwa jalannya pemerintahan dalam negara kita, sudah diatur oleh sistem dengan segenap mekanismenya sendiri. Di samping para intelektual ada lembaga resmi yang secara resmi punya kompetensi untuk itu, dalam hal ini DPR. Dengan mekenisme demokrasi yang sudah kita sepekati, jalannya suatu pemerintahan, siapa pun presidennya, tentu tidak mungkin keluar dari ‘halauan dasar’ yang dibuat bersama DPR tersebut. Dalam konteks demikian, itulah sebabnya tanggung jawab para intelektual memang hanya sebatas tanggung jawab moral, dan bukan institusional. M
Meskipun demikian, teruslah menyampaikan kritik kapan pun dan kepada siapa pun. Kritik yang dilakukan dengan standar akademik yang sama (adil) tanpa pilih kasih. Sebagai manusia intelek yang lekat dengan objektivitas, sebuah kritik tentu juga harus objektif. Objektivitas sebuah kritik mengharuskan kita melihat sebuah objek dari dua sisi. Dalam konteks jalannya pemerintahan, dua sisi itu ialah: keberhasilan dan kekurangan. Tentu hanya pada aspek kekurangan inilah sebuah kritik diperlukan. Dan, yang lebih penting, dengan penuh sportivitas, sebuah kritik tetap harus dilakukan dengan standar budaya nusantara dengan segenap tata kramanya. Merdeka!