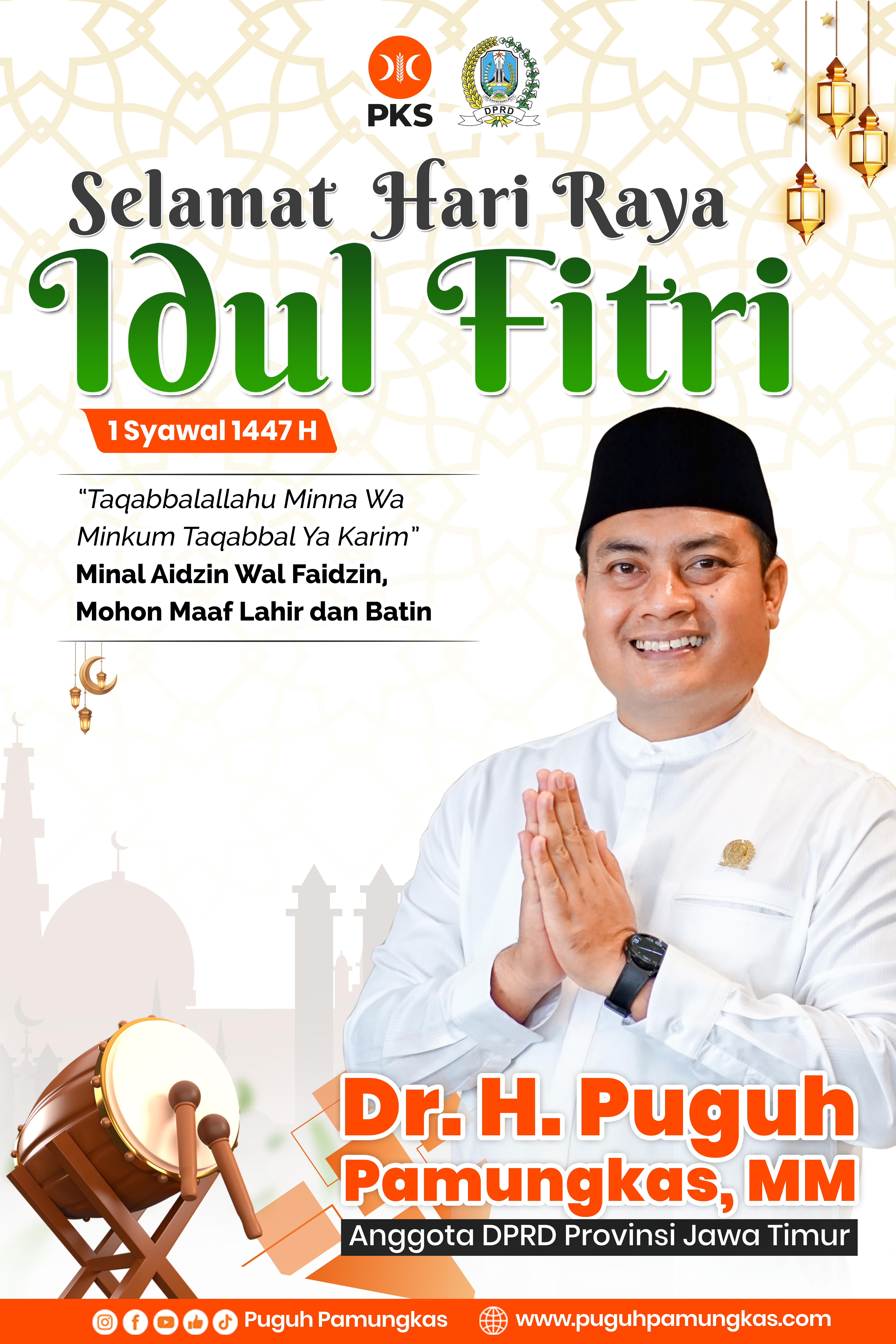Oleh: Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Setidaknya Ada 4 ibadah penting yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Dzulhijjah ini. Ibadah itu adalah: menunaikan ibadah haji, berpuasa di hari Arafah, melaksanakan salat idul adha, dan menyembelih kurban. Masing-masing mempunyai landasan naqli (wahyu) baik dari Al Quran maupun As Sunnah ( Al Hadits). Ibadah haji didasarkan antara lain atas Firman Allah swt surat Ali Imran ayat 97 yang artinya: “Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” Para Ulama sepakat bahwa hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai kemampuan. Para fukaha mengartikan kemampuan meliputi: mampu dari segi biaya, mampu dari segi fisik dan mampu melakukan perjalanan (termasuk keamanan).
Berpuasa di hari Arafah didasarkan antara lain, adanya sebuah hadits rasulullah SAW, bahwa “Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyuro (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu” (HR. Muslim).” Dari semua dalil mengenai puasa Arafah ini, para ulama pada umumnya mengambil ketetapan (istimbat) hukum, bahwa puasa Arafah hukumnya sunat.
Dilaksanakan kebiasaan salat id (idul adha), antara lain didasarkan atas firman Allah dalam Al-Quran yaitu yang terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah SWT berfirman yang artinya, “Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.” Ayat ini menggambarkan pentingnya melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalil ini sekaligus juga menjadi dalil disyariatkannya berkorban. Meskipun dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah, pada umumnya para fukaha menentapkan hukum salat id dan berkurban sebagai ibadah sunat, kecuali Imam Abu Hanifah yang menghukumi kurban dengan hukum wajib, kecuali jika sedang dalam keadaan bepergian (musafir). Sedangkan, mayoritas ulama (Jumhur), termasuk 2 pentolan Madzhab Hanafi ( Abu Yusuf dan Muhammad Al Hasan) menghukumi kurban dengan sunat muakad, yaitu suatu amalan yang sangat dianjurkan yang dapat berfungsi sebagai penyempurna amalan lain.
Gairah Berkurban
Pada umumnya, di antara 4 amalan tersebut, yang paling populer di tanah air, bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, ialah pelaksanaan kurban. Ibadah ini sangat populer karena harus melibatkan jutaan hewan dan keterkaitannya dengan pihak lain. Binatang tersebut tidak lain ialah hewan ternak yang dijadikan sebagai kurban. Karena menyangkut hewan, maka memerlukan manajemen tidak hanya berskala lokal tetapi juga nasional.
Seiring dengan kemakmuran dan kesadaran berkorban semakin tinggi, maka yang menjadi masalah berikut adalah mengenai ketersediaan jutaan hewan sekaligus kesehatannya. Pada saat yang sama juga tidak bisa dilepaskan dengan aspek perdagangan. Logika ekonomi pun berlaku, yaitu hukum ”demand “ dan “supply”. Ketika keduanya berjalan ‘tidak normal’ akan terjadi ketidakstabilan dan berpotensi menimbulkan ‘kegoncangan’. Oleh karenanya, jangan heran jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, maka gara-gara hewan kurban bisa menjadi isu nasional dan bukan mustahil akan berubah menjadi isu politik yang ujungnya akan mengkambinghitamkan pemerintah. Hanya saja ketika “suasana aman” sepertinya dianggap biasa-biasa saja seolah masalah ketersediaan hewan ini alami saja tanpa sedikit pun peran pemerintah atau pejabat terkait.
Inovasi Fikih
Akan tetapi di tengah gegap gempita kesadaran berkurban ada pertanyaan nakal muncul, dalam bentuknya yang sekarang, ke depan apakah praktik korban ini masih relevan atau perlukah praktik berkurban ini perlu dimodifikasi disesuaikan dengan perkembangan zaman?
Sebagaimana diketahui, bahwa praktik berkurban selama ini hanyalah menyembelih hewan kurban. Beberapa waktu lalu juga terdapat video viral yang dibuat oleh seorang, sebut saja “Bapak Tua”. Narasi nakalnya dan bernuansa SARA itu pada pokoknya berisi kritikan terhadap praktik kurban yang tidak sejalan dengan tradisi leluhur. Sebagai ‘non muslim’, kritikan yang disampaikannya tentu sebuah sikap konyol. Bagi kebanyakan kaum muslimin kritikannya mengenai wilayah syariat tentu dapat dianggap sebagai penodaan–atau kini lazim disebut penistaan–agama.
Di negeri ini tercatat pernah ada sederet nama yang menjadi korban apa yang biasa disebut “penodaan agama”. Kebanyakan mereka harus mengalami nasib mengenaskan karena harus menginap di hotel prodeo setelah menjalani proses hukum. Jangankan dari orang non muslim, para tokoh ilmuwan sekaliber Nurcholis Madjid, Ahmad Wahib, dan Gus Dur pernah dibuly oleh sesama muslim karena kritikan-kritikan segarnya tentang praktik keagamaan yang dianggapnya menyimpang atau bahkan tidak sesuai dari substansi syariat atau ironisme praktik keagamaan kebanyakan kaum muslimin.
Akan tetapi, benarkah kritikan itu “Bapak Tua” itu mutlak salah. Sebagai muslim yang bijak tentu tidak perlu menanggapi kritikan siapa pun mengenai agama kita. Apalagi sampai harus main hakim sendiri (eigenrichting). Di negeri demokrasi ini, sesuai konstitusi (Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945), setiap orang memang diberi kebebasan mengeluarkan pendapat. Hanya hukumlah yang memberikan batasan-batasan. Apabila dianggap melanggar rambu-rambu hukum, hak kita hanya melaporkan kepada lembaga yang berwenang.
Terlepas dari kekonyolan “Bapak Tua” dalam konten yang dibuatnya, dalam praktik berkorban ini, tampaknya kita perlu melakukan kritik sendiri (selfcritic). Beberapa praktik pelaksanaan kurban di lapangan tampaknya sering bersifat nisbi. Apa yang tepat dilaksanakan di suatu daerah sering tidak pas jika dipraktikkan di daerah lain. Yang demikian wajar karena penerapan syariat merupakan bagian dari persoalan ijtihad. Masalah ijtihad mengakibatkan polarisasi pendapat sekaligus perbedaan implementasi. Atau, dapat dikatakan masalah penerapan syari’at sebagian besar masuk wilayah fikih. Kebanyakan kita memang sering kurang tertarik untuk membedakan mana yang syariat dan mana yang pelaksanaan syariat. Salat 5 waktu dan ketentuan waktunya merupakan syariat tetapi begaimana penerapannya, seperti cara bertakbir, cara sujud, membaca cara bacaan yang harus dibaca adalah masalah ijtihad. Karena masalah ijtihad maka terdapat berbabagai pendapat fukaha.
Syariat sejatinya tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Pengertian ini diperjelas oleh Manna’ al-Qhaththan yang menyebut syariah sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dalam praktik syari’ah sering disandingkan dengan pembahasan fikih. Fikih secara umum diartikan sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat melalui interpretasi Al Qur’an dan As Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah pendapat ulama. Perbedaan mendasar keduanya, bahwa syariat bersifat abadi sedangkan fikih bersifat lokal dan temporal.
Dalam konteks ibadah kurban, perintah kurban merupakan syari’at. Akan tetapi, bagaimana hukum melaksanakannya, cara melaksanakannya, dan segenap penerapan kurban lainnya merupakan fikih. Di kebanyakan tempat, membagi daging kurban harus dibagikan berupa daging mentah. Pendapat ini tampak mengakar sangat kuat karena memang mempunyai landasan teks-teks formal aturan fikih. Pembahasan kurban ini, dalam fikih biasanya disandingkan dengan pembahasan aqiqah, yaitu sembelihan yang diperuntukkan atas kelahiran bayi. Pada umumnya para fukaha berpendapat, bahwa salah satu perbedaan pembagian daging korban dan aqiqah ialah bahwa daging kurban dibagikan secara mentah (nayyian)sedangkan daging aqiqah diberikan dalam keadaan sudah siap saji atau sudah dimasak ( thabhan). Akibat ada ketentuan ini, maka hampir di semua tempat, daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Di banyak tempat pula, praktik demikian sering menimbulkan problem baru. Bahkan pernah terjadi tragedi memilukan mengenai hal ini, seorang menjadi korban (meninggal) karena daging korban.
Akan tetapi, di daerah tetentu kini sudah mulai membuat inovasi berbeda. Inovasi itu ialah membagikan daging kurban sudah dalam bentuk menjadi lauk siap saji, seperti dibuat rendang. Ketika penulis masih kuliah (1980-an) di IAIN Yogyakarta (UIN, sekarang) saat kampus menyembelih hewan kurban, tidak dibagi dalam bentuk daging mentah melainkan sudah di masak. Orang-orang sekitar kampus diundang pada malam harinya untuk makan bersama. Acara yang sebelumnya diisi pengajian umum itu selalu ‘sukses’ dari tahu ke tahun. Dasar pemikirannya, yang penulis tangkap dari praktik tersebut, yang paling utama ialah efisiensi, yaitu agar orang miskin jangan mendapat beban tambahan akibat menerima daging kurban. Beban tambahan itu ialah harus mencari uang lebih dari biasanya, karena harus membeli bumbu dan segenap biaya lain agar daging yang diterima bisa layak menjadi santapan. Oleh karena itu, pembagian daging kurban dalam bentuk rendang kemasan tentu dapat dianggap sebagai sebuah perkembangan inovasi.
Inovasi tersebut, ke depan mungkin perlu ditingkatkan ke hal-hal yang strategis. Inovasi tersebut misalnya, karena kurban hanya sunat, bagi suatu komunitas tertentu yang masyarakatnya (jumlahnya) sudah terdata dengan baik mungkin perlu dibatasi jumlah hewan yang dijadikan kurban. Kalau 10 ekor kambing saja sudah cukup, mengapa harus 25 ekor kambing. Kelebihan animo berkorban tersebut bisa digunakan untuk amal lainnya seperti memberikan beasiswa anak yatim atau hal-hal strategis lainnya yang justru lebih wajib.
Inovasi lain, mungkin perlu sentralisasi penyembelihan. Yang demikian ditempuh agar masjid atau musala seteril dari berbagai efek negatif, seperti penyakit akibat banyak kotoran yang ditidak dibersihkan secara maksimal. Sering terjadi akibat penyembelihan hewan, berhari-hari masjid bau anyir dan mengganggu kenyamanan orang salat. Ustaz yang biasanya sangat respek dengan persoalan najis, saat musim kurban tampaknya sedikit abai dengan persoalan najis. Yang demikian, juga belum lagi jika ditinjau dari aspek kesehatan. Atau, sering kita saksikan, akibat ditangani oleh tenaga yang tidak profesional, hewan yang akan disembelih kabur.
Hal-hal di atas, hanyalah sebagian persoalan yang masih tersisa dalam praktik pelaksanaan kurban. Dan, yang lebih penting hal-hal itu sebenarnya menyangkut bidang fikih yang perlu dibuat inovasi. Inovasi ini dibuat bukan dimaksudkan melawan syari’at yang memang abadi dan berlaku sampai kapan pun. Para ulama yang mempunyai kedalaman ilmu agama tampaknya perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan (ahli kesehatan dan penguasa setempat ) membahas ini. Atau, praktik manajemen kurban ini, biar tetap saja berjalan seperti bentuknya sekarang? Hanya urun rembuk. Wallahu a’lam.