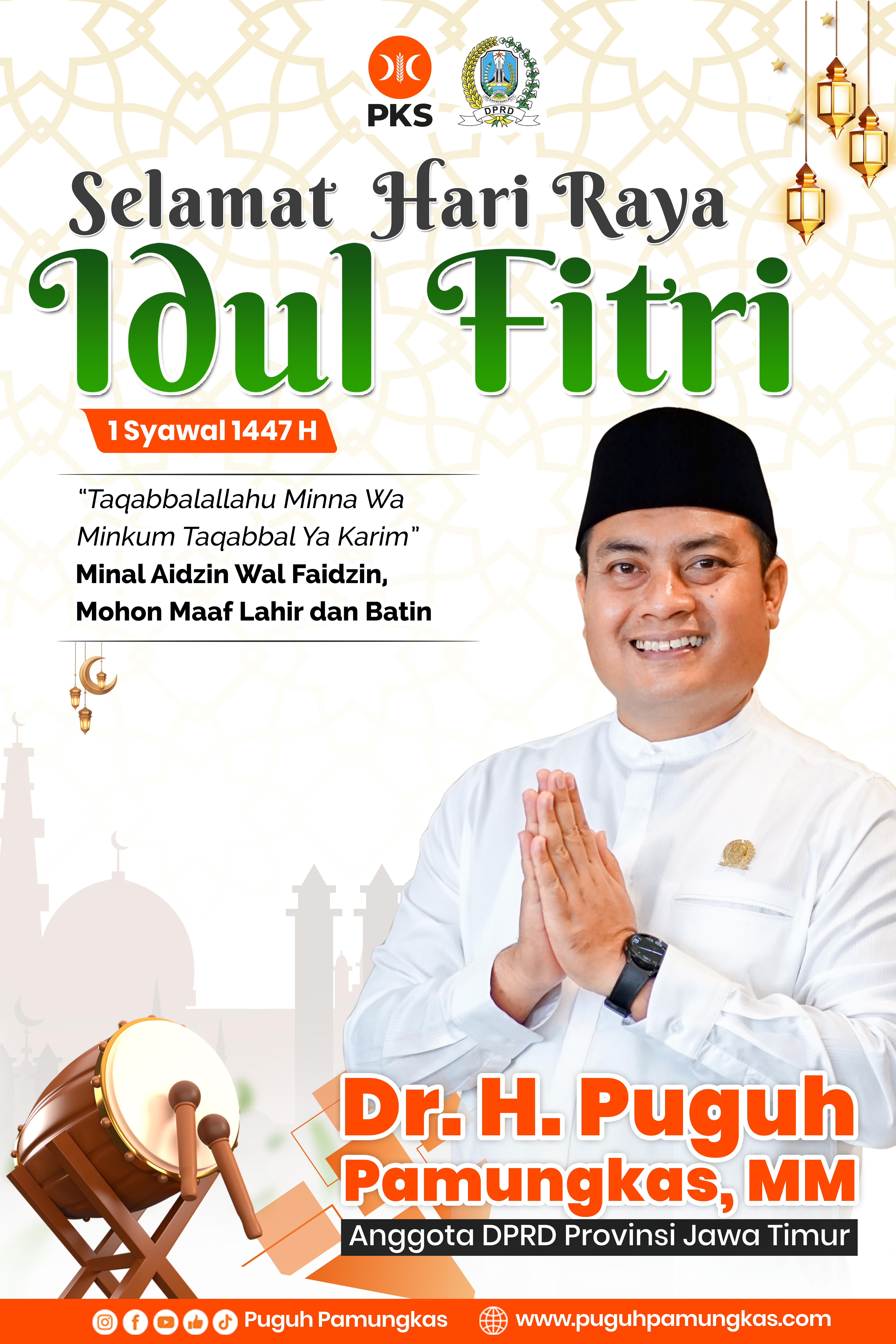Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas IA)
“Anak jadah tidak akan diterima amal ibadahnya, sebelum membunuh ayahnya”, begitu sang (oknum) guru ngaji itu memberikan tausiyah di masjid waktu itu. Yang dimaksud anak jadah itu tidak lain, dalam penjelasan berikutnya, adalah anak yang lahir akibat perzinaan. Kalimat bernuansa aneh sekaligus mengerikan itu terus menghantui pikiran saya yang waktu itu masih anak-anak (Sekolah Dasar). Sampai akhirnya ketika menginjak SLTA kujumpai sebuah buku materi pelajaran agama (hadits) bahwa statmen sang guru ngaji itu memang mempunyai ‘dasar hukum’. Hati saya segera lega ketika hadits tersebut muncul dalam pembahasan hadits-hadits palsu. Pikiran saya juga lebih tenteram ketika kemudian sang Guru hadits menyampaikan salah satu hadits nabi yang mengatakan, bahwa “setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (bersih dari dosa).” Tanpa mengurangi rasa hormat (ta’dhim) kepada sang ustadz—yang setiap usai salat selalu saya doakan–saya memang perlu mengingat itu lagi dan menjadikannya sebagai pembuka tulisan ini.
Pikiran berontak tentang eksistensi anak hasil zina tersebut, sampai saat masih mengusik rasa keadilan saya dan sudah tentu juga anak-anak tidak berdosa akibat hubungan intim kedua orang tuanya di luar nikah. Meskipun dapat memperoleh akta kelahiran, tetapi tetap saja menyisakan persoalan akibat tidak bisa mencantumkan nama sang ayah yang secara biologis menjadikan sebab ibunya mengandung dan lalu melahirkannya. Si anak dengan pikiran polosnya masygul ketika menyaksikan akta kelahiran yang dimilikinya tidak seperti milik teman-temannya. Milik teman-temannya semua mencantumkan nama ayah dan ibunya tetapi miliknya tidak. Di tengah pergaulan sesama teman itupun dia sering mendapat gunjingan sinis, bahwa dia lahir tanpa ayah. Beban sosial anak itupun terus terasa ketika harus memasuki jenjang demi jenjang pendidikan (sekolah) yang tetap menuntut akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran masuk sekolah. Rasa sedih dan pilu si anak terus membayangi di tengah suasana keramaian sekolah dengan beban mata pelajaran yang harus digeluti. Sesekali, dalam hatinya kiranya menjerit dan memanggil-manggil “Mama, mana ayahku……”
Tentang cerita anak yang minta pengakuan status hukum itu memang melegenda ketika ada seorang pesohor (selebriti) wanita menghiba secara hukum agar anak yang dilahirkan akibat hubungan ‘pernikahan’ dengan sang pejabat tinggi terkenal waktu itu, diakui sebagai anaknya (yang sah). Perjuangannya memperoleh keadilan dianggapnya kandas sekaligus menemui jalan buntu sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi ‘bermurah hati’ mengabulkan permohonan uji materi salah satu pasal undang-undang perkawinan (sebut saja UU Nomor 1 Tahun 1974) yang berkaitan tentang status anaknya.
Ihwal anak luar nikah atau anak zina, memang telah menjadi perdebatan hukum sejak dulu. Para fuqaha telah membahasnya panjang lebar menganai hal ini. Pada umumnya fukaha sepakat bahwa anak zina bisa dinasabkan kepada ibu yang melahirkan. Ketika sampai pada pertanyaan apakaah anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Jumhur (Ḥanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Ḥanabilah) berpendapat, bahwa tidak bisa isbat nasab anak yang dilahirkan di luar batas minimal kehamilan, termasuk anak zina. Artinya anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, meski laki-laki yang menjadi penyebabnya mengakuinya.
Hanya saja, meskipun terdapat banyak ulama yang memandang nasab anak zina tidak bisa diakui oleh ayah biologis, terdapat pula ulama yang membolehkan anak zina diakui oleh ayah biologis. Salah satu ulama kontemporer yang berpendapat tentang bolehnya anak biologis Muḥammad Abu Zahrah. Beliau berpendapat, bahwa seorang ayah biologis dapat mengakui anak biologisnya sebagai anaknya yang sah. Beliau menambahkan, seorang laki-laki berzina dengan perempuan dan hamil, maka laki-laki itu boleh menikahi perempuan tadi, dan ditetapkan nasab anak tersebut dengan syarat harus ada pengakuan atau ilḥāq atas anak tersebut. Metode ilḥaq merupakan metode pengakuan anak atau disebut pula dengan iqrar bi al-nasb. Cara penetapan nasab anak melalui ilḥaq yaitu seorang laki-laki mengakui dengan suka rela bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya merupakan anaknya. Dalam kasus serupa, laki-laki yang telah berzina dengan sorang perempuan, ia bisa mengakui anak biologisnya sebagai anaknya yang sah. Hanya saja ia dianjurkan tidak secara terus terang mengakui anak itu sebagai anak hasil zinanya. Mengapa diperlukan klausul demikian tidak lain, salah satu hikmahnya, juga dalam rangka menjaga sisi psikis anak.
Kata biologis diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan reproduksi. Jadi, ayah biologis secara sederhana berarti bapak atau laki-laki sebagai memiliki hubungan darah secara biologis tanpa melihat pada sisi nilai hukum. Artinya, ayah biologis menunjukkan pada makna seseorang yang memiliki anak yang secara biologis memiliki keterikatan darah namun belum tentu memiliki keterikatan secara hukum Islam. Oleh sebab itu, penggunaan istilah ayah biologis biasanya disertakan dengan eksistensi anak zina. Sebab, anak zina sudah jelas memiliki ayah biologis tetapi tidak memiliki ayah yang sah secara hukum.
Abu Zahrah sebenarnya berada pada satu pemahaman dengan pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa anak zina secara prinsip tidak memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan ia lahir (ayah biologisnya). Tetapi Abu Zahrah berbeda dengan jumhur ulama mengenai boleh tidaknya pengakuan nasab anak zina oleh ayah biologis melalui lembaga pengakuan (ilḥāq/ iqrar bi al-nasab). Bagi Abu Zahrah, meskipun awalnya anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tapi anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya itu dengan jalan pengakuan. Pengakuan tersebut menurut Abu Zahrah terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan, syarat-syarat tertentu, yaitu laki-laki itu tidak menerangkan bahwa anak yang diakuinya itu hasil dari perzinaan, selain itu anak yang diakui itu harus lahir kurang dari 6 (enam) bulan, sebab jika anak itu lahir lebih dari enam bulan, maka ayah biologis tidak perlu mengakui anak tersebut. Sebab, secara zahir anak tersebut lahir sudah dalam batas minimal kehamilan.
Konsekuensi dari keterhubungan nasab anak zina dengan ayah biologis pascapengakuan itu menggakibatkan ayahnya wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sebab nafkah anak tersebut adalah karena hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan minimal ada tiga jenis sebab kewajiban nafkah, yaitu karena pernikahan, karena kepemilikan, dan sebab kekerabatan. Anak zina yang sudah diakui ayah biologisnya mengakibatkan timbulnya hubungan kekerabatan, sehingga secara hukum ayah biologis wajib menafkahkan harta kepada anak hasil zinanya yang sudah ia akui (ilḥāq) itu. Demikian pula dalam kasus warisan, jika ayah biologis sudah mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tanpa keterusterangan bahwa anak tersebut hasil dari hasil zina, maka anak tersebut mewarisi harta ayahnya dan ayahnya mewarisi hartanya. Muhammad Abu Zahrah juga menyinggung pendapat yang diambil oleh Ibn Taimiyah dan Ishaq bin Rahawaih, bahwa anak zina bisa mewarisi harta dari pezina dengan syarat pezina mengakui anak itu sebagai anaknya. Sekilas pendapat Guru Besar al-Azhar yang demikian itu, telah diulas oleh Desi Suryani dalam skripsi hasil penelitiannya yang diberi judul “Pengakuan Nasab Anak Zina oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilhaq” (Analisis Pendapat Muḥammad Abu Zahrah). Ada baiknya para pengadil dan pemerhati hukum menelusuri lebih lanjut mengenai hal itu. Sebab, pendapat yang demikian tampaknya sejalan dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan aspirasi hukum yang berkembang di masyarakat saat ini.
Ilustrasi wacana hukum di atas dikemukakan dengan maksud untuk menegaskan kepada kita, bahwa masalah status anak luar kawin tidak bisa ‘diputuskan’ dengan pendekatan hukum secara hitam putih. Apalagi, sekedar dengan logika-logika pasal-pasal aturan hukum tertulis yang statis itu. Sumber dari mana aturan-aturan itu berasal, sekaligus wacana yang berkembang, perlu dilihat oleh para pengadil. Hal demikian dimaksudkan, agar para pengadil tidak terjebak ke dalam dogmatis hukum sebaimana aliran hukum murni Hans Kelsen–yang kini ada kecenderungan ditinggalkan orang. Bukankah, setiap pengadil—sesuai amanat Pasal– wajib hukumnya mencermati nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Sikap dikhotomis, tentang suatu persoalan hukum menurut hukum negara, di satu pihak, dan menurut hukum agama (Islam), di pihak lain, tidak boleh terus-menerus dikembangkan. Hukum yang dipraktikkan oleh peradilan mana pun di negeri ini, harus dalam kerangka penegakan hukum negara yang ada. Kita sering mengklaim suatu persoalan hukum sebagai bertentangan dengan hukum Islam, tetapi kita lupa bertanya, hukum Islam yang mana? Menurut Jumhurkah atau menurut siapa. Dengan keyakinan, bahwa persoalan hukum yang ada sebagai masalah ijtihadi, ternyata pilihan pilihan pendapat hukum lain (warisan fuqaha) masih ada. Mencari pilihan pendapat–yang sesuai dengan perkembangan hukum masa kini– itulah yang mestinya kita kembangkan. Kalau tidak bukan mustahil nasib hukum Islam pun bisa bernasib sama dengan aliran hukum yang dianggap kaku sehingga akan ditinggalkan orang. Wajah Islam sebagai rahmatan lil alamin, salah satunya dapat dilihat dari tampilan wajah hukumnya. Wallahu A’lam.