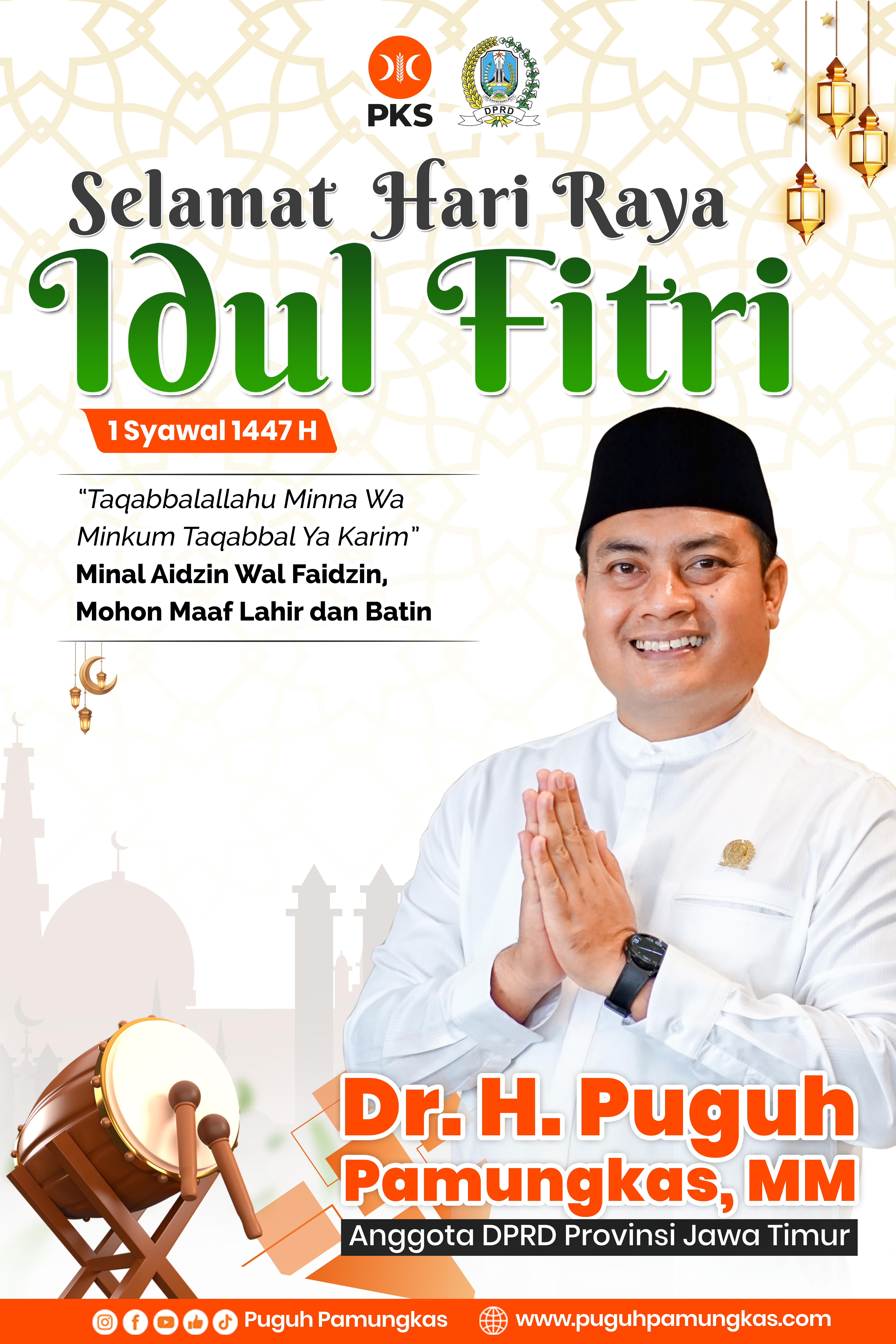Oleh : Drs.H. Asmu’i Syarkowi, M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pagebluk yang berasal dari bahasa Jawa diberi arti “wabah” (penyakit). Lebih lanjut, Muhammad Ibnu Pratista, sebagaimana dimuat dalam Gama Cendekia UGM ( gc.ukm.ugm.ac.id, 06/07/2020) pagebluk adalah sebutan untuk suatu wabah penyakit yang sedang terjadi. Kata “pagebluk”, menurutnya, berasal dari kata dasar “gebluk” atau “bluk” dapat berarti jatuh tersungkur, tumbang, atau dapat juga disebut ledakan.
Dengan akar keta demikian, pagebluk menggambarkan suatu kondisi banyak korban berjatuhan, bertumbangan, ataupun jatuh tersungkur yang terjadi secara serentak bahkan berskala luas, yang karena besarnya hal tersebut maka menimbulkan korban yang banyak, sehingga menyerupai arti “gebluk” yaitu ledakan. Selanjutnya, dapat disimpulkan, bahwa pagebluk merupakan suatu istilah lokal yang digunakan untuk menyebut istilah pandemi. Oleh karena itu, ketika wabah coronavirus desaes 2019, yang kini lebih dikenal covid-19 ini mewabah, banyak orang Jawa pun menyebut sebagai pagebluk.
Kini kesimpangsiuran mengenai virus corona telah menjadi santapan kita sehari-hari. Jagad medsos rupanya telah sangat ‘berjasa’ menyebarluaskan beritanya mengalahkan mas media cetak standar (mainstream). Sayangnya, berita tersebut sudah susah dibedakan, antara yang “hak” dan “batil” (hoax), sudah barang tentu, terutama bagi orang awam yang kurang ilmu. Pada saat yang sama, tampaknya isu pandemi kini sudah tidak netral. Banyak orang pintar di negeri ini yang karena perbedaan politik ikut memutarbalikkan informasi seharusnya. Dengan kata lain, kini banyak penumpang gelap memanfaatkan isi pandemi ini. Penumpang gelap ini tidak jarang juga memakai sentimen SARA. Narasi-narasi ilmiah dan legitimasi dalil-dalil agama sengaja dibuat untuk menyerang pemerintah sehingga menjadi teror tersendiri bagi percepatan penanggulangan pandemi covid-19 yang kini sudah memasuki tahun kedua ini. Program kewajiban penerapan protokol (prokes) dengan 3 M ( memakai masker, mencuci tangan, dean menjaga jarak), bahkan kini menjadi 5 M ( ditambah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas), sangat susah dilaksanakan, sebagiannya disebabkan oleh pihak-pihak tersebut.
Akan tetapi, tahukah kita ada kerumunan akibat pertemuan ‘resmi’ dan diam-diam ‘harus’ terus berlangsung pada saat kebanyakan orang ‘ketakutan’ melakukan kontak dengan orang lain? Pertemuan itu ialah kerumunan orang di kantor pengadilan (agama) yang hampir terjadi setiap hari selama 5 hari kerja. Tanpa ada rasa was-was, bahkan takut sedikit pun, masyarakat terus saja mendaftar perkara ke pengadilan agama. Pada saat yang sama, sebagai instansi pelayanan hukum, pengadilan juga tidak kuasa menolak mesyarakat untuk mencari keadilan. Jargon: ”Tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh”, tampaknya saat ini benar-benar menjadi kenyataan. Masyarakat tetap saja mendatangi pengadilan meskipun ada gonjang-ganjing dunia akibat serangan covid-19. Dan, gonjang-ganjing itu, kini serasa nyaris meruntuhkan langit, ketika satu demi satu masyarakat luas, termasuk insan pengadilan harus menemui ajal karena Covid-19 varian baru.
Sebagaimana pernah penulis kemukakan pada tulisan sebelumnya yang telah terpublikasi, kegiatan orang datang di kantor pengadilan pada dasarnya ada 3 kelompok. Pertama, kelompok orang yang akan mendaftar perkara. Kedua, kelompok orang yang antri sidang, dan ketiga kelompok pengunjung sidang lainnya, seperti mengantar sidang keluarganya atau menjadi saksi. Untuk kelompok pertama masyarakat belum terikat oleh norma. Mereka dapat memilih meneruskan mendaftar atau mengurungkannya dengan alasan tertentu. Kendali menentukan datang atau tidak datang ke pengadilan masih berada di pihak masyarakat sendiri. Bahkan, adanya isu virus yang mengganas ini mestinya justru bisa dijadikan momentum untuk mengurungkan perceraian. Masyarakat perlu melakukan refleksi, bahwa di masa-masa sulit di era pandemi ini, justru menjadi momentum untuk menguatkan kekompakan keluarga, bukan malah bercerai dengan segala akibat buruknya.
Akan sangat elok pula, jika momentum ini juga dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan itu misalnya, di era pandemi ini pendaftaran perkara dibatasi, terutama untuk perkara dispensasi kawin yang memang setiap perkara sering harus melibatkan kehadiran banyak orang. Langkah ini diambil, juga dimaksudkan untuk menunjang efektivitas keberlakuan undang-undang, khususnya mengenai batasan minimal usia kawin, dalam hal ini Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dari umur 16 tahun menjadi umur 19 tahun.
Untuk kelompok kedua, yaitu masyarakat penunggu sidang tentu tidak bisa demikian. Para penunggu sidang ini harus mengikuti sidang sesuai antrian yang didapat. Pada saat demikian, masyarakat kelompok ini, yang biasanya datang sejak pagi, tidak tahu sampai pukul berapa bisa pulang meninggalkan gedung pengadilan sehingga segera terbebas dari kerumunan orang. Sedangkan, masyarakat kelompok ketiga, yaitu pengunjung sidang, memang bisa mengatur diri datang atau tidak datang ke pengadilan. Akan tatapi, ketika sebagai saksi masyarakat kelompok ini tidak serta merta bisa menghindar untuk tidak datang ke pengadilan begitu saja. Sebab, ketika dalam hal suatu peristiwa harus dibuktikan dengan saksi, sehingga saksi tersebut sangat menentukan, kehadirannya di pengadilan bersifat imperatif. Begitu urgennya kehadiran saksi ini sebab sesuai Pasal 141 HIR, saksi yang tetap tidak mau hadir setelah dipanggil secara sah oleh pengadilan, hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dibawa (paksa) oleh polisi ke pengadilan.
Beberapa waktu lalu memang ada kebijakan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, persidangan elekronik ini ternyata tidak serta merta dapat diimplementasikan karena benyak prasyarat yang belum mendukung. Padahal, kalau bisa diterapkan Perma, yang di-lounching 6 Agustus 2019 lalu mestinya dapat mengurangi terjadinya kerumunan. Dalam praktik hakim pemeriksa juga tidak bisa dengan sembarangan mempraktikkan sidang-sidang virtual. Bagi para pihak ketidakmauan memilih beracara dengan sidang virtual sering disebabkan oleh kenyataan, bahwa cara ini dirasakan ribet, di samping karena keterbatasan pengetahuan tentang teknologi. Di samping itu, ada pula sebagian orang, karena alasan-alasan tertentu, justru lebih memilih “sidang secara manual”, meskipun sidang secara virtual lebih efisien. Kasus persidangan HRS di PN Jakarta Timur beberapa waktu lalu, manjadi salah satu contohnya.
Dengan potret harian situasi dan kondisi pengadilan di atas, penyebaran virus via lembaga peradilan ternyata seperti yang kita duga sebelumnya. Sejak pandemi hingga tulisan ini dibuat sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan warga pengadilan meninggal dunia. Hampir setiap hari di aplikasi WhatsApp warga pengadilan terisi berita kematian hakim dan aparat pengadilan lainnya. Data terbaru yang bersumber dari corona.mahkamahagung.co.id. sebagaimana dikutip oleh detik.news (04/07/21) juga tidak kalah heboh. Sebanyak 180, aparat Mahkamah Agung, termasuk 3 Hakim Agung saat ini dinyatakan positif covid-19.
Terkait covid-19 ini mewaspadai keberadaan para pejabat peradilan (Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pejabat lainnya) juga tidak boleh diabaikan. Kelompok ini di luar hitungan 3 kelompok masyarakat di atas. Mereka rata-rata berasal dari daerah lintas kabupaten bahkan provinsi dan bahkan sebagian lagi lintas pulau. Di mana letak urgensinya? Bukan tidak mungkin ketika harus berbaur dengan masyarakat umum di angkutan umum tanpa disadari mereka ‘terinfeksi’. Pada saat yang sama, di tengah ‘tekanan’ rutinitas pekerjaan yang kini semakin kompleks ini, kesempatan mengontrolkan kondisi kesehatan semakin terbatas. Praktis mereka biasanya hanya bisa sempat pergi ke dokter hari Sabtu. Gambaran jadwal hariannya, bagi yang berasal dari lintas kabupetan adalah hari Minggu siang harus sudah di perjalanan menuju tempat kerja. Senin sampai Jum’at pada jam kerja harus bekerja di kantor. Pada Jum’at malam harus kembali berada lagi di perjalanan untuk pulang ke rumah.
Dengan alasan kondisi badan, ekonomis dan keamanan, sebagian besar dari merekapun sering memilih angkutan umum dari pada membawa kendaraan pribadi. Pada saat demikian itulah, petaka itu mungkin dimulai. Berbaur dengan penumpang lain yang tidak diketahui latar belakangnya akan menjadi persoalan baru. Siapa yang dapat menjamin para pejabat peradilan tersebut tidak terpapar sementara pihak Dinas Perhubungan pun belum melakukan tindakan nyata melakukan upaya-upaya pencegahan di terminal-terminal maupun pengawasan penerapan prokes di setiap kendaraan umum (Bus dan Angkot) yang beroperasi. Di saat pusat memberikan ‘dispensasi’ boleh meliburkan sekolah dan beberapa daerah memberikan kelonggaran untuk ’ngantor’ di rumah, tidak demikian halnya pengadilan. Penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) dengan karakteristik tupoksi yang ada, sangat tidak gampang diterapkan di dunia peradilan. Berbeda dengan pengadilan banding dan kasasi, dengan gambaran uraian tugas yang ada dan formasi hakim yang tidak merata, pengadilan tingkat pertama sepertinya hampir tidak mungkin menerapkan WFH.
Ancaman terpapar virus ‘mematikan’ itu sangat disadari oleh para pejabat peradilan. Akan tetapi, apalah daya sehingga kekhawatiran itu tinggallah kekhawatiran. Terutama, aparat pengadilan tingkat pertama yang memang harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bertawakal kepada Yang Mahakuasalah satu-satunya senjata pemungkas yang masih tersisa, dengan suatu kalimat tambahan : “ yang terjadi terjadilah.” Ketika baru-baru ini terbit Surat Edaran Dirjen Peradilan Agama Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan WFH Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, para insan peradilan tingkat pertama sebenarnya juga ingin ikut disapa via aturan demikian, terutama terkait dengan PPKM. Tetapi, sayang aturan itu hanya untuk internal pejabat/ pegawai di lingkungan Dirjen. Aturan WFH itu, ternyata sama sekali tidak berlaku bagi peradilan tingkat pertama yang seluruh aparatnya, di samping harus bergelut dengan berkas-berkas, setiap hari harus kontak langsung dengan masyarakat luas. Akan tetapi, dari pada tidak ada dan akan semakin menambah korban, untuk merespon situasi darurat yang ada, aturan itu memang patut segera dibuat. Sekalipun hanya mengatur sebagian aparat. Di tengah dilematika mengatur implementasi tupoksi peradilan dengan segala kompleksitasnya, mungkin ini pengamalan kaidah fikih: “mala yudraku kulluhu la yutroku kulluh” ( yang tidak bisa didapat semua, jangan pula ditinggal semua). Sekilas situasi demikian menggambarkan betapa nestapanya aparat peradilan. Akan tetapi, ketika peradilan sebagai wadah bagi para wakil tuhan di muka bumi, semua aparat peradilan harus tetap semangat dan kompak. Jika tuhan tidak pernah capek mengurus hambanya, termasuk menegakkan keadilan. Yang telah diklaim sebagai wakil-Nya (hakim) dan seluruh jajaran terkait, juga harus tetap semangat, dengan segenap risiko apapun yang mungkin terjadi. “Hasbunallahu wani’mal wakil”.