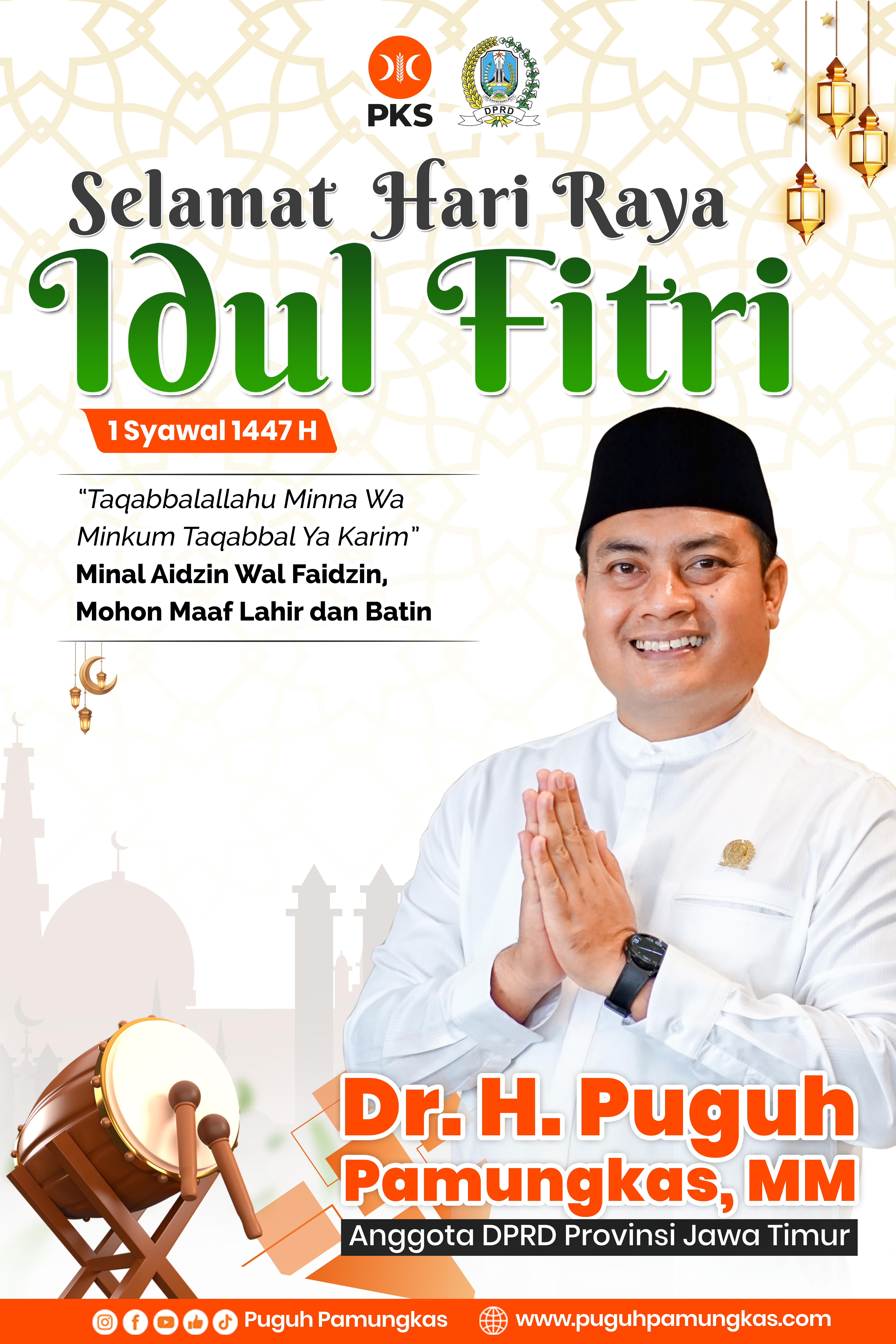Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Majalah Gatra (No. 34 Tahun XV edisi 2-8 Juli 2009) pernah menulis tentang proses peradilan pidana atau pengenaan hukum positif yang baru pertama kali terjadi terhadap masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD). Kasus berawal dari terjadinya keributan antara dua kelompok mengenai urusan sewa menyewa mesin gergaji yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dari kedua belah pihak.
Kasus yang menjadi duduk perkara menurut cetatan media bermula dari Kelompok Madjid atau Mata Gunung menyewa mesin pemotong kayu dari Celitai. Harga sewa yang dispekati Rp800.000,00. Harga tersebut sudah dibayar tetapi masih kurang Rp 50.000,00. Dari sinilah awal terpicunya bentrokan antara dua kelompok ini yang berujung pada kematian 4 orang. Madjid melunasi kekurangan tersebut. Tetapi, dalam proses pelunasan inilah terjadi “salah ucap” yang membuat pihak Celitai tersinggung dan menyulut terjadinya keributan berdarah yang mengakibatkan 4 nyawa melayang. Persoalan ini sebenarnya sudah diselesaikan dengan hukum adat. Celitai diwajibkan membayar 1.000 helai kain dan Madjid harus menyerahkan 500 helai kain”. Terhadap penyelesaian melalui hukum adat yang telah mereka patuhi secara turun temurun tersebut, pihak berwajib menilai bahwa penyelesaian secara hukum adat tersebut harus pula diselesaikan secara hukum positif. Selengkapnya Majalah Gatra menulis bahwa menurut hukum adat, seharusnya masalah ini selesai. Tetapi hukum positif negara mengatakan lain. Keduanya diciduk polisi dan dikenai tuntutan hukum positif yang pada akhirnya hanya membuat proses perdamaian antar dua kelompok yang bertikai menjadi “tidak sempurna” karena ada salah satu pihak yang “wanprestasi” dan “melewatkan” prosesi maaf-maafan untuk menyempurnakan penyelesaian kasus ini secara adat. Hal ini terjadi karena mereka keburu diciduk oleh aparat hukum.
Penyelesaian perkara pidana terhadap masyarakat adat Suku Rimba melalui proses peradilan pidana sesuai ketentuan KUHP dan KUHAP tersebut, telah menarik perhatian banyak pihak bahkan mengundang perdebatan di kalangan akademisi hukum. Majalah Tempo Online (23 Maret 2009) melansir bahwa ada yang berpendapat bahwa penerapan hukum pidana tersebut sudah tepat karena hukum pidana nasional harus berdiri di atas pranata hukum lainnya termasuk hukum adat, namun ada pula yang berpendirian terhadap masyarakat hukum adat yang telah memiliki dan mematuhi hukum tidak tertulis secara turun temurun, tidak dapat serta merta dilakukan pengenaan hukum positif, melainkan harus membuat mereka mengetahui dan mengerti terlebih dahulu mengenai hukum positif”.
Paparan mengenai kasus SAD di atas jelas memberikan gambaran kepada kita tentang perlunya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum, seperti: apakah hukum, apakah fungsi hukum, dan apakah tujuan hukum? Jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut selama ini sangat bervariasi. Variasi jawaban tersebut timbul kerena perbedaan sudut pandang yang pada akhirnya telah menimbulkan sejumlah aliran dalam ilmu hukum. Aliran-aliran tersebut pada akhirnya menempatkan penganutnya pada kutup-kutup yang berlainan. Bahkan, sebagian di antaranya ada yang cenderung bersifat antagonistis. Cara pandang mengenai perlu tidaknya perselisihan SAD dari kelompok Celitai dan kelompok Majid yang dibawa ke ranah hukum positif di atas, jelas menjadi salah satu contoh mengenai perbedaan cara pandang mengenai hukum.
Hukum Adat dan Globalisasi
Indonesia adalah negara kepualauan terbesar di dunia. Luasnya, menurut data dari Kementrerian Koordinanator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaiamana dikutip detiktravel (20 Juli 2022) jumlah luas wilayah darat dan laut mencapai 8.300.000 kilometer persegi. Meskipun dari seluas itu sekitar 62 persen terdiri dari laut dan perarairan, namun dengan jumlah penduduk yang nyaris menembus angkanga 300 juta, Indonesia tetaplah sebuah negara besar. Yang menarik adalah jumlah angka penduduk yang mendiami sekitar 16.056 pulau itu menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga terdiri dari 1.340 suku bangsa.
Aneka suku bangsa yang ada, jika mengacu pada Cicero-yaitu ubi Societas Ibi Ius– jelas mempunyai hukumnya masing-masing. Pertanyaan mendasarnya, lantas bagaimana kedudukan hukum positif kita di antara hukum-hukum adat yang ada itu? Dalam konteks negara hukum, haruskah hukum positif yang ada mengalahkan hukum-hukum yang ada atau dapat berjalan secara beriringan? Jawabannya memang akan selalu menjadi perdebatan hukum oleh para ahli hukum. Pro kontra seputar penanganan kasus SAD ke pengadilan negara menjadi bukti polarisasi pendapat itu.
Terlepas dari pro dan kontra yang ada, berkat kemajuan teknologi informasi dan dinamika penyebaran penduduk, suku-suku bangsa dengan berbagai adatnya mau tidak mau terkena imbasnya. Akibat arus globalisasi yang menempatkan dunia laksana bola kecil ini, kini hampir tidak ada manusia yang dapat menutup diri dari perubahan, baik sikap dan perilaku. Kepala suku atau para tokoh adat memang boleh membuat proteksi sedemikian rupa. Bahkan proteksi ini secara formal juga dikumandangkan para penguasa dengan jargon-jargon, seperti “menjaga tradisi dan kearifan lokal” serta “pelesterian budaya”. Akan tetapi, generasi muda yang terus berinteraksi dengan dunia luar lambat laun tetapi pasti akan mengalami perubahan pola pikir (mindset).
Perubahan pola pikir ini kadang-kadang tidak jarang harus, kalau tidak disebut sebagai berawanan, berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di komunitas sukunya. Suku Jawa sebagai suku mayoritas, telah mengalami hal ini. Akibat kepadatan penduduk dengan segala risiko yang ditimbulkan, berakibat mengalami mobilitas ke berbagai pelosok tanah air bahkan dunia. Akibat terjadinya akulturasi budaya, kini banyak generasi muda Jawa mengalami perubahan cara pandang terhadap tradisi luhurnya sendiri. Akibat negatifnya memang banyak anak muda yang kurang mengenal budayanya sendiri sedangkan akibat positifnya orang Jawa di mana pun berada terlihat lebih bersikap terbuka dan toleran dengan siapa pun. Oleh karena itu, akibat kemajuan teknologi yang terus berlangsung dengan berbagai dampaknya, yang demikian sangat mungkin menimpa suku-suku lain betatapa pun protektifnya.
Sutandyo Wignyosubroto (Guru Besar Hukum Unair) sebagaimana dikutip oleh Zuhdi Muchdhor, telah megingatkan bahwa dinamika globalisasi adalah terjadinya perubahan pola-pola hubungan antar manusia dalam organisasi kehidupan, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi (bisnis) yang semula berada pada ruang lingkup lokal (yang kongkret) menuju ruang lingkup regional dan nasional dan bahkan mengglobal (yang semakin abstrak). Dalam konteks hukum adat, sangat mungkin sebagai konsekuensi akhir dari situasi demikian, juga akan berdampak kepada keterancaman eksistensi hukum adat.
Dari paparan di atas tentu kita ingat Roscoe Pound yang menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.
Sebagai sebuah negara besar dengan ribuan suku bangsa dan dinamika masyarakat akibat globalisasi dengan segenap dampaknya, memang sulit mempertahankan hukum adat secara rigid. Ketika hukum positif sebagaimana diberlakukan oleh penguasa formal, pelaksaan hukum adat secara murni akan berakibat terjadinya dualisme hukum. Akibat berikutnya, seorang yang melakukan kesalahan juga akan menerima 2 hukuman sekaligus: di satu pihak akan terkena hukum positif (negara) dan dipihak lain pada saat yang sama juga terkena hukum adat (suku). Kasus SAD di atas menjadi contohnya.
Kondisi semacam ini tidak mustahil akan menyentuh hukum yang berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama. Di Papua misalnya sudah terjadi, ada kasus seorang istri pada perkara cerai talak, di samping menuntut nafkah iddah mut’ah juga menuntut pemenuhan mahar secara adat yang mungkin pernah diperjanjikan. Para Hakim di tempat lain, sangat mungkin mengalami hal demikian. Mengenai hal itu, hukum materiil Islam pasti belum menulisnya. Akan tetapi bukankah di atas hukum ada filsafat hukum dan di atas fikih ada ushul fikih. Oleh karena itu berikut perdebatan berikutnya ialah mengenai bagaimana Hukum adat ketika berhadapan dengan hukum Islam. Mengenai hal ini, ushul fikih jauh-jauh hari telah memberikan konsep dasar mengenai kedudukan al-‘urf dan berikut lahirnya qaidah: al-‘Adah muhakkamah. Implementasinya bagaimana, bergantung penguasaan para hakim agama mengenai hukum Islam berikut kreativitasnya (ijtihad) dengan segenap pengetahuan pendukungnya.
Selamat bertugas.