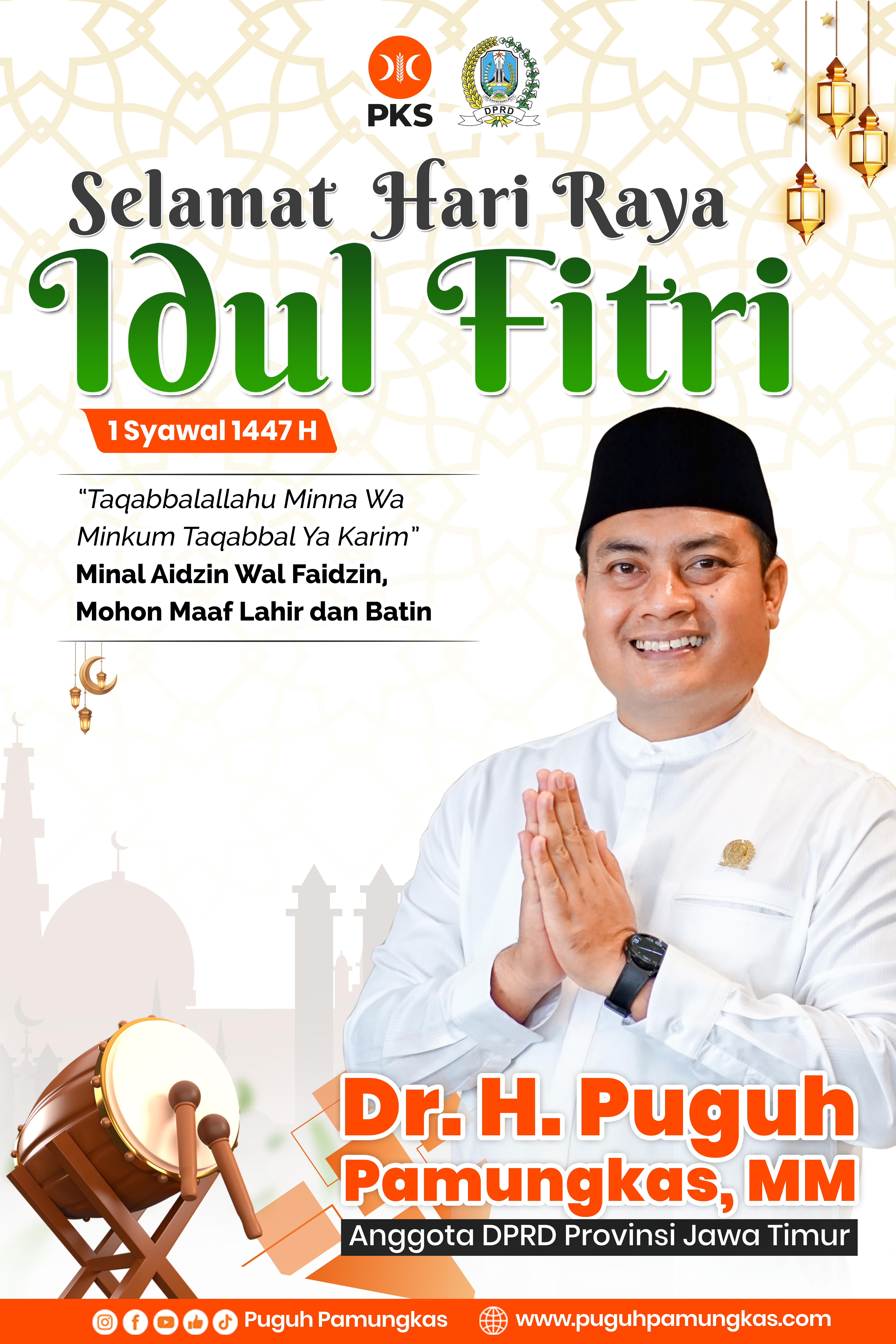Jakarta, beritalima.com| – Beberapa waktu lalu, masyarakat kembali dikejutkan oleh kasus memilukan di Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah). Seorang siswa kelas VII SMPN 1 Geyer, bernama ABP (12 tahun), meninggal dunia akibat dugaan perundungan oleh teman sekelasnya di lingkungan sekolah.
Kejadian tragis ini bukanlah insiden spontan, nenek korban sempat melaporkan sejak 28 Agustus 2025, ABP sudah menjadi sasaran ejekan dan tindakan bullying atau perundungan kepada pihak sekolah. Meski upaya mediasi internal pernah dilakukan, situasi memburuk dengan pelaku yang berbeda, hingga akhirnya korban tutup usia di dalam kelas (11/10/2025).
Kasus ini menjadi peringatan serius tentang lemahnya mekanisme pengawasan dan pencegahan kekerasan di institusi Pendidikan. Ini bukan sekadar pelanggaran moral dan hukum, melainkan juga bentuk ekstrem dari kekerasan dan perundungan yang merusak esensi pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi taman belajar, justru berubah menjadi ruang traumatik bagi korban. Fenomena ini menegaskan bahwa budaya kekerasan masih bersemayam di balik dinding lembaga pendidikan yang mestinya menanamkan nilai kasih sayang dan empati.
Di tengah semangat mewujudkan pendidikan yang merdeka dan berkarakter, masih ada bayang‐bayang gelap yang menghantui ruang kelas, yakni perundungan. Ia hadir dalam bentuk ejekan yang menoreh luka, tatapan yang merendahkan, hingga sentuhan fisik yang menyakitkan. Padahal sekolah seharusnya menjadi taman belajar yang aman dan menggembirakan, bukan ladang ketakutan bagi para murid yang hanya ingin tumbuh dan bermimpi.
Perundungan bukanlah hal baru, tetapi dampaknya kian meluas, terutama di era digital. Menurut UNESCO, hampir sepertiga siswa di dunia pernah mengalami perundungan. Di Indonesia sendiri, laporan KPAI 2023 mencatat 1.433 kasus perundungan di satuan pendidikan. Lebih mencemaskan lagi, Survei PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat kelima tertinggi dari 81 negara dalam kasus perundungan di sekolah. Sekitar 41 persen siswa mengaku sering di-bully, jauh di atas rata-rata global. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan jeritan yang perlu segera didengar dan direspon dengan kesadaran kolektif.
Perundungan memiliki wajah yang beragam. Ia bisa muncul dalam bentuk fisik seperti memukul atau menendang, dalam bentuk verbal seperti mengejek dan mengolok-olok, atau bahkan dalam bentuk sosial seperti mengucilkan dan menyebar gosip. Yang kini kian marak adalah cyberbullying, bentuk perundungan di dunia maya yang tidak mengenal ruang dan waktu. Satu komentar jahat atau unggahan bernada hinaan bisa menyayat harga diri seseorang lebih dalam dari sekadar luka di kulit.
Mengapa perilaku ini terus berulang? Banyak faktor yang berkelindan. Dari sisi individu, pelaku kerap memiliki keinginan mendominasi atau kurang empati. Sebaliknya, korban sering dianggap “berbeda” dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dari sisi keluarga, pola asuh yang keras atau abai, serta minimnya komunikasi yang hangat, dapat menjadi benih lahirnya perilaku agresif.
Sekolah pun memiliki tanggung jawab besar. Ketika kebijakan anti-perundungan tidak jelas, atau guru menutup mata terhadap perilaku merundung, maka kekerasan akan tumbuh subur dalam diam. Begitu pula masyarakat yang masih menoleransi ejekan, bahkan menjadikannya hiburan, serta media yang terkadang menormalisasi kekerasan verbal demi sensasi. Semua ini adalah ekosistem yang harus dibenahi bersama.
Untuk menanggulangi perundungan, dunia telah belajar dari banyak praktik baik. Finlandia, misalnya, memiliki program KiVa, yang fokus mengubah perilaku siswa yang menyaksikan perundungan. Mereka diajak untuk tidak mendukung pelaku dan berani berpihak pada korban. Dengan demikian, pelaku kehilangan “panggung sosial”-nya.
Norwegia melalui program Olweus menegakkan aturan tegas dan mengawasi area-area rawan di sekolah. Di Jepang, pendekatan moral dan tanggung jawab kolektif membuat seluruh komunitas kelas merasa ikut bertanggung jawab atas tindakan perundungan. Sedangkan Australia memilih jalur pendidikan positif melalui Positive Behaviour for Learning (PBL), yang menumbuhkan perilaku baik dengan penghargaan dan dialog pemulihan.
Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar pengetahuan, tetapi juga laboratorium karakter. Indonesia pun perlu melangkah ke arah yang sama. Gerakan seperti Advo Asik Camp Happy tanpa Bully bisa menjadi ruang inspiratif untuk menghidupkan semangat anti-perundungan di sekolah, dengan pendekatan yang menyenangkan dan penuh empati.
Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media -empat pusat Pendidikan- memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan. Keluarga perlu menanamkan empati sejak dini, mengajarkan anak menghargai perbedaan dan tidak menertawakan kekurangan orang lain. Sekolah wajib memiliki sistem pelaporan yang aman dan guru yang tanggap serta terlatih dalam menangani kasus perundungan.
Masyarakat harus menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, di mana tidak ada anak yang merasa ditinggalkan karena perbedaan status atau kemampuan. Media pun memegang peranan penting dalam menanamkan kesadaran publik, melalui konten yang membangun dan bukan yang mempermalukan. Platform digital harus menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas terhadap cyberbullying, bukan sekadar membiarkan komentar jahat mengalir tanpa kendali.
Namun, lebih dari sekadar pencegahan dan penanganan, yang kita butuhkan adalah budaya belajar baru. Budaya yang menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan gembira bagi semua. Sekolah aman berarti bebas dari segala bentuk kekerasan -baik fisik, verbal, maupun digital. Ia juga aman dari bencana, dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Di ruang yang aman, anak bisa tumbuh dengan rasa percaya diri dan tidak takut menjadi dirinya sendiri.
Sekolah nyaman adalah tempat di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan punya ruang untuk berkembang. Kenyamanan itu tumbuh dari relasi sosial yang hangat, sarana yang mendukung, dan suasana belajar yang tidak menekan. Di sekolah yang nyaman, murid tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga matang emosional.
Dan sekolah gembira adalah ruang di mana anak-anak boleh tertawa, bermain, berkreasi, dan bermimpi. Gembira belajar bukan berarti tanpa disiplin, melainkan belajar dengan rasa ingin tahu yang hidup. Gembira bermain bukan sekadar bersenang-senang, tetapi membangun solidaritas dan imajinasi. Sementara gembira mengembangkan bakat berarti memberi ruang pada setiap anak untuk menemukan potensinya sendiri.
Budaya belajar yang aman, nyaman, dan gembira tidak mungkin terwujud bila masih ada satu saja anak yang pulang ke rumah dengan mata sembab karena ditertawakan teman-temannya. Ia juga takkan tumbuh bila guru atau orang tua masih menutup mata, berpura-pura tak tahu bahwa ejekan kecil bisa jadi awal luka besar.
Maka, tugas kita bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem yang membuat perundungan tidak mendapat tempat untuk tumbuh. Setiap anak berhak atas ruang belajar yang menumbuhkan, bukan yang menakutkan. Sudah saatnya sekolah menjadi taman jiwa -tempat setiap individu tumbuh dengan rasa aman, belajar dengan nyaman, dan tertawa dengan gembira. Di sana, ilmu tidak sekadar diajarkan, tapi juga dihidupkan dengan kasih sayang dan empati.
Mari kita wujudkan sekolah tanpa bully. Sekolah yang tidak hanya mencetak generasi pintar, tetapi juga generasi yang punya hati, yang menghargai sesama, menjaga perasaan, dan menolak kekerasan dalam bentuk apa pun. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya tentang nilai di rapor, tetapi tentang bagaimana kita belajar menjadi manusia.
Oleh” Mariman Darto, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen RI