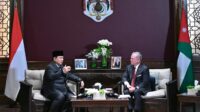Jakarta, beritaima.com| -Di hadapan jenazah yang disalatkan dan tanah yang masih basah, kita tak boleh lagi bersembunyi di balik kalimat “bencana alam semata. Bencana ini juga cermin keputusan politik, ekonomi, dan etika kolektif kita, tentang pembangunan yang menyingkirkan keberlanjutan demi kecepatan.
Ini bukan sekadar bencana alam. Ini bencana ekologis: peristiwa alam yang diperparah oleh kerusakan lingkungan yang telah lama kita biarkan. Bencana ekologis berubah menjadi bunuh diri ekologis jika manusia terus merusak alam melampaui daya pulihnya.
Misalnya menebang hutan tanpa jeda, meracuni air dengan limbah industri, mengikis tanah tanpa kendali, dan menutup mata pada peringatan ilmiah. Pada akhirnya, kita sendiri yang perlahan menghancurkan fondasi tempat hidup kita berdiri.
Malam itu, langit di atas Sumatra tidak hanya gelap. Ia tampak seperti sedang menimbang sesuatu yang suram. Hujan turun bukan sebagai rintik-rintik, melainkan sebagai tirai air yang menghantam atap rumah, tanah, dan dada manusia yang bahkan tak sempat memahami apa yang sedang terjadi.
Di sebuah desa di Tapanuli, seorang ayah berlari sambil menggendong putrinya yang baru lima tahun. Mereka baru saja mendengar suara menggelegar dari hulu, suara yang tak pernah ia dengar seumur hidupnya. Lebih menyerupai gunung runtuh daripada sekadar banjir.
“Tunggu Ayah, tunggu Ibu.” Suara kecil itu tenggelam dalam dentuman arus yang membawa batang-batang kayu sebesar tubuh manusia. Ketika air bah datang, ia datang seperti makhluk buas yang tak memberi waktu. Ia merobek jembatan, menelan rumah, menyapu manusia tanpa pandang usia atau sejarah hidup. Sang ayah selamat karena berpegang pada pohon besar. Anaknya pun selamat. Namun istrinya hilang, ditelan malam dan air.
Di Aceh, seorang remaja terjebak di atap rumah bersama dua adiknya. Mereka mengayunkan senter ke arah langit yang sepenuhnya pekat.Tidak ada suara selain hujan. Tidak ada cahaya selain kilat. Helikopter tak mungkin menembus badai. Jalan-jalan sudah lenyap.
Di Sumatra Barat, para pengungsi menyaksikan rumah mereka perlahan terseret arus, seperti perahu tua yang dilepaskan dari dermaga terakhirnya. Malam itu, Air dan Tanah seakan bersatu untuk menguji manusia. Dan Sumatra pun menangis. Bencana itu tidak hanya jatuh dari langit. Ia lahir dari gabungan antara langit yang murka dan bumi yang telah lama kita lukai.
Dilaporkan lebih dari 442 jiwa meninggal, lebih dari 75.219 mengungsi, lebih dari 106.806 terdampak total Rumah roboh. Akses terputus. Listrik padam. Hidup bergantung pada bantuan darurat. Hujan ekstrem dipicu Siklon Tropis Senyar, badai langka yang terbentuk di Selat Malaka. Ini peristiwa yang hampir tidak pernah terjadi dalam puluhan tahun. Air turun dengan intensitas yang tak mampu ditampung tanah. Sungai meluap. Lereng jenuh air.
Material dari kawasan hulu, yang selama ini dibiarkan rusak, ikut terbawa. Aceh, Sumut, dan Sumbar berada dalam satu garis nasib. Wilayah itu dihantam tanpa ampun oleh air yang datang dari gunung dan hutan yang sudah tidak lagi utuh. Bencana tidak pernah datang sepenuhnya sendiri. Ia lahir dari pertemuan sebab dan akibat, dari keputusan masa lalu yang kita biarkan membusuk.
Ada tiga akar utama tragedi ini. 1. Cuaca Ekstrem yang Tak Lagi Terduga, Siklon Tropis Senyar, anomali iklim, memicu hujan yang melampaui batas normal. Curah hujan dua minggu jatuh dalam dua hari. Kita hidup di era ketika langit kehilangan ritmenya. Ia tidak lagi menetes pelan, tetapi menumpahkan murka sekaligus.
Perubahan iklim bukan teori. Ia menjadi tangis ratusan keluarga. David Wallace-Wells menggambarkan dunia yang memanas sebagai dunia yang makin tak stabil. Pola hujan berubah, badai membesar, dan cuaca menjadi kekuatan liar. Tragedi Sumatra adalah potongan nyata dari masa depan itu.
2. Deforestasi dan Luka di Hulu yang Tak Sembuh. Hutan-hutan di Batang Toru dan kawasan hulu telah lama digunduli. Kayu diambil. Tanah dilucuti. Ekosistem dicabik. Ketika hujan turun, tanah tak lagi menjadi penyangga; ia berubah menjadi lumpur, menjadi peluru, menjadi arus maut. Banjir bukan hanya air. Banjir adalah air yang kehilangan hutan. Batang-batang kayu besar yang hanyut bukan kebetulan. Itu adalah sidik jari dari perusakan yang berlangsung sistemik.
Jared Diamond dalam Collapse menyatakan: peradaban runtuh ketika hutannya hilang, tanah tak lagi menyerap air, lereng rapuh, dan banjir bandang menjadi tak terelakkan. Sumatra sedang menapaki pola klasik itu.
3. Pemukiman di Zona Bahaya dan Tata Ruang yang Gagal. Desa berdiri di bantaran sungai, kaki bukit, lereng retak, di daerah yang sejak awal adalah panggung bagi bencana. Peta risiko tersedia, tetapi tak pernah sungguh-sungguh diterjemahkan menjadi tindakan. uPerencanaan ruang berubah menjadi ritual administratif, bukan kompas keselamatan. Ketika arus datang, warga hanya punya dua pilihan: lari atau hilang.
Bencana membesar bukan hanya karena alam mengamuk. Ia membesar karena kita tidak siap. Saatnya menagih tanggung jawab: audit ekologis hulu, relokasi wajib zona bahaya, pengawasan tata ruang, dan anggaran yang berpihak pada pencegahan, bukan seremoni. Di antara lumpur yang mengering. Di antara pondasi rumah yang kini tak memiliki dinding. Di antara jenazah yang ditemukan. Kita belajar sesuatu.
Bencana ini bukan hanya tentang kehilangan. Ia adalah tentang ingatan, bahwa alam selalu mengingatkan kita dengan cara yang tegas. Dan seperti semua pelajaran besar, ia menyimpan kemungkinan harapan. Jika tragedi ini ingin menjadi titik balik, maka Indonesia harus bergerak dari pembangunan yang memaksa alam tunduk menuju pembangunan pro-ekologis. Ini pembangunan yang berjalan seirama dengan hukum alam, bukan melawannya.
Apa itu pembangunan pro-ekologis? Ia adalah paradigma yang meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar keputusan pembangunan. Ini bukan tentang angka APBN semata, atau kecepatan proyek semata, apalagi ambisi politik jangka pendek. Pembangunan pro-ekologis bukan pembangunan yang “membiarkan” alam bertahan. Ia adalah pembangunan yang menggantungkan keberlanjutannya pada kesehatan alam itu sendiri.
Apa bentuk konkretnya? Ada empat langkah besar. 1. Memulihkan Hulu: Reforestasi Total Berbasis Ilmu. Hulu adalah jantung. Jika jantung rusak, tubuh runtuh. Restorasi harus dilakukan bukan secara simbolik atau dokumentatif, melainkan benar-benar ilmiah (penanaman spesies endemik, pemulihan jalur satwa, larangan absolut pembukaan lahan di zona retensi air dan pengawasan satelit harian). Tanpa hutan yang pulih, Sumatra akan selalu berada di ujung tanduk.
2. Tata Ruang Berbasis Risiko, Bukan Kebiasaan. Pemukiman di bantaran sungai tidak boleh lagi dinegosiasikan. Relokasi harus menjadi bahasa keberpihakan negara. Setiap izin harus melewati: audit risiko hidrometeorologi, audit geologi, simulasi banjir 50–100 tahunan. Pembangunan pro-ekologis berarti berani mengatakan “tidak” pada proyek yang berbenturan dengan keselamatan warga.
3. Infrastruktur Hijau: Sabuk Hidup di Sepanjang Sungai. Yang memimpin bukan beton, tetapi alam yang dipulihkan (rorak di perbukitan, sabuk hijau di sepanjang sungai, ruang retensi alami, pemulihan meander sungai, pengerasan tanah berbasis vegetasi—bukan semen). Infrastruktur hijau bekerja dalam sunyi, tetapi menyelamatkan nyawa lebih banyak daripada dinding beton mana pun.
4. Teknologi untuk Pencegahan, Bukan Reaksi. Sensor curah hujan, radar, pemetaan hulu, AI prediksi banjir, dan sistem peringatan dini hingga tingkat desa. Teknologi harus mengubah mentalitas: dari “menunggu bencana” menjadi “mencegah bencana.” Di wilayah rawan, setiap menit berarti kehidupan.
Tragedi Sumatra bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Di berbagai belahan dunia, pola serupa berulang, memperlihatkan bagaimana keputusan politik dan ekonomi yang mengabaikan ekologi selalu berujung pada biaya kemanusiaan yang tak tertanggung. Kita bisa belajar banyak dari negara lain. Montana, Amerika Serikat, adalah contoh nyata.
Wilayah yang dulu dijuluki “Big Sky Country”, tempat pegunungan bersalju dan padang rumput tampak seperti surga dunia, kini memikul luka ekologis yang dalam. Puluhan tahun penambangan logam berat meninggalkan limbah arsenik dan merkuri di sungai-sungainya; hutan yang dulu permai ditebang tanpa perhitungan.
Di sana, tanah peternakan terkikis hingga menjadi gurun tipis. Montana membuktikan bahwa bahkan negara kaya sekalipun, jika abai, bisa berubah dari lanskap indah menjadi wilayah yang rusak parah. Ini peringatan bahwa keruntuhan tidak memilih benua ataupun tingkat kemakmuran.
Karena itu, jangan sampai kita sebagai bangsa, karena ketidakpedulian, ketidaktahuan, atau sikap meremehkan, mengulangi pola yang sama dan berjalan menuju bunuh diri ekologis. Sejarah Montana telah menjadi alarm: surga bisa runtuh jika manusia merasa kebal terhadap hukum alam. Indonesia harus belajar sebelum terlambat, sebelum keindahan hulu, sungai, dan hutan kita tinggal nama dan angka statistik bencana. Kita masih bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang menjaga, bukan menghancurkan.
Denny JA, Ketua Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, Jakarta, 2 Desember 2025
Referensi
- David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth: Life After Warming, Penguin Random House, 2019.
- Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking Press, 2005.