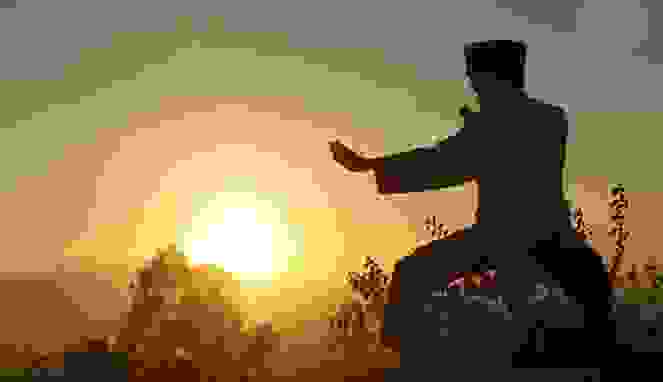Mohon maaf, saya tidak tertarik bergumam tentang situasi negeri ini, yang tokoh-tokohnya mulai ‘nyinyir’; janji sana-sini dengan dimuarakan pada kepentingan rakyat. Toch gaji pegawai negeri tetap ngeri, cabe tak terbeli, beras di musim panen masih melambung, dan tarif listrik terus merambat tanpa sosialisasi. “Aku memiliki negeri ini, tapi tak pernah merasakan nikmatnya hidup di negeri warisan Majapahit ini,” Pak Sakerah ketus, lalu diam. Maka ia hanya ingin menulis ‘cinta’)
Cinta: Tak lebih dari kebencian yang ditunda. Seorang Bandung Bondowoso misalnya, adalah kisah yang dibangun dari akar cinta untuk memiliki atau dimiliki oleh angannya, dan Jongrang sebagai tumbal dalam proses persyaratan yang mustahil: 1000 candi dalam semalam. Ketika syarat itu tak terpenuhi, cinta tertusuk membenam dalam sebuah kebencian yang sangat.
Cinta itu mengundang kebencian, dan menyuburkannya entah dalam angan atau nyata. Sebuah sinisme hati yang tertoreh. Dan, al-Adawiyah adalah sebuah misal yang menemukan cinta-Nya, namun membenci sesamanya. Ketika cintanya hanya dimuarakan kepada Sang Khalik, ia telah mengorbankan segalanya dalam bentuk kebencian yang disusun dengan kalimat sederhana “Saya tidak bisa membagi cinta”—yang disampaikan dengan bergetar, tapi menyayat hati pendengarnya.
Ada banyak hal yang berderet-deret, mengapa ‘pelampiasan’ cinta seseorang kepada ‘rencana’ pasangannya tak tergapai. Satu deret yang mudah dihafal, “Belum pantas”—yang bisa ditafsir lingkungan sosial kita belum berkenan. Misalnya, ia telah memiliki pasangan yang dalam agama apapun, kecuali di zaman purba ketika tenun baju belum ditemukan, memiliki dua ‘pejantan’. Tidak layak, oke. Tapi lebih tidak layak ketika hasrat untuk memiliki dimuarakan kepada cinta. Dan, poliandri di masa kini adalah kata yang (hanya) tercantum di dalam kamus, yang semestinya telah dihapus dalam daftar kata ketika agama-agama mulai diyakini umat manusia.
Kisah menarik yang patut diajukan dalam tulisan ini, Layla Maimunah yang menyeberangi sungai Tigris hanya berjalan kaki, di atas air. Ia meyakini, Tuhan mencintainya. Oleh karena cinta-Nya kepada Maimunah, dan cinta Maimunah kepada-Nya; apa yang ia minta selalu terkabul hanya dengan sepotong doa, “Layla mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Layla”—dan air beriak, lalu tenang, dan ia menyeberangi Tigris dengan hanya berjalan kaki di atas air. Sementara, seorang tukang perahu terkagum-kagum, lantaran ia sendiri tidak mampu melakukan sebagaimana Maimunah lakukan. Padahal, doa cinta itu keluar dari mulut tukang perahu, dan mengajarkannya kepada Layla Maimunah. Sebuah sinisme cinta yang tak terukur, dan Tuhan Mahatahu segalanya!
Qais ‘al-Majnun’ yang memilih Layla sebagai kekasihnya, adalah sebuah deret kisah yang unik dan menarik dicerna. Kisahnya mencintai Layla, sebagai jembatan untuk menuju Sang Khalik, sebagaimana al-Hallaj yang menyatukan sesuatu yang tidak padu, dan Syekh Siti Jenar yang ‘manunggaling kawula Gusti’.
Oleh karena cintanya yang menyatu, bukan hanya kepada makhluk tapi kepada Sang Pemilik, binatang buas pun tunduk dan hormat. Mereka tetap memiliki rasa yang sama, dan ‘perasaan’ itu menjadi abadi—tidak seperti Li Changgeng di wilayah Jiangyou, Provinsi Sichuan, Tiongkok sebagaimana ditulis Goenawan Mohamad dalam ‘Tempo’ (24/5/2015). Ia seorang juru tangis pada pekabungan. Dan, ia mendapat upah dari pekerjaannya. Li Changgeng mencintai pekerjaannya. Ia pun bisa menata ritme-tangis: mengaung-ngaung, menjerit-jerit dan meronta-ronta dengan perasaan yang amat dalam dengan berbagai improvisasi sesuai dengan besaran upah yang diterimanya. Tapi lama-kelamaan Li mengaku: “Akhirnya kami tidak memiliki perasaan.”—hilang dan menjelma menjadi cinta pada uang.
Di zaman Jepang, seorang nelayan Pasongsongan, Ki Nasran, bercerita. Ia terdampar sampai ke pesisir Dungkek ketika menangkap ikan. Untuk menyambung hidupnya, ia menjual tangis pada rumah duka keluarga Cina di Dungkek. Ia tidak merasa kehilangan, atau duka pada siapapun; tapi Ki Nasran hanya mencintai uang untuk menyambung hidupnya. Memang, pada mulanya ia iku berduka, dan lama-kelamaan duka itu menghilanng.
Tidak di ‘kids zaman now’, Kiai Masurat bisa memiliki 10 isteri, dengan sebuah ‘istana’ ratusan kamar untuk semua isterinya. Asisten rumah tangga disediakan di setiap kamar sang isteri, dan tukang-tukang bangunan yang setiap hari bekerja memperbaiki tembok yang kadang gempil, atau sekadar mengelap meja-makan. Juru masak, dan beberapa mobil yang diparkir di lantai atas siap menemani sang permaisuri, atau padmi. Dan, jika Kiai Masurat berlaku adil, ia tidak akan pernah memiliki permaisuri dan padmi; keduanya sama, setara dan mendapat perlakuan yang sebanding. Tapi, adakah ia bisa membagi cinta kepada kesemua isterinya? Tidak pernah terungkap dari seorang Kiai Masurat yang asli Lenteng, Sumenep itu sampai akhir hayatnya. Ataukah sepuluh isterinya itu sebagai idaman belaka?
Di ‘kids zaman now’ malah berkembang, manusia idaman lain bukan hanya milik suami. Tapi juga isteri. Tidak sedikit seorang isteri ingin memiliki suami lebih dari satu, sebagaimana yang dilakukan suaminya. Mungkin mereka mengira, Tuhan tidak adil menerapkan hukum-hukum agama. Seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah menulis tugas akhirnya dengan sumber tokoh: “Demi keadilan, dan atas nama HAM, wanita juga diperkenankan memiliki lebih dari seorang suami. Apalagi hanya lelaki idaman. Sebab, Tuhan Mahaadil. Dan hanya kita saja yang tidak bisa berlaku adil, menempatkan wanita pada posisi yang terpinggirkan, dan selalu rugi, tidak sama, dan hanya menelan ludah ketika melihat laki-laki memiliki lebih sebagaimana wanita juga berkeinginan.”—sebuah simpulan dari pemeradilan untuk laki-laki dan wanita, yang di ‘kids zaman now’ memang diperjuangkan, sementara di zaman orde yang berderet dianggap menista.
Jika seorang isteri menginginkan lebih dari satu pasangan, maka ia hidup di ‘kids zaman now’—yang semakin tak karuan. Dan, jika seorang wanita bersuami masih bergenit-genit dengan angan-angan ‘melampaui batas’ kewajaran, ia barangkali lupa bahwa rumah idamannya semakin sempit: 1×2 meter.
Telepas dari itu semua, apakah Anda masih punya cinta? Ataukah sudah hilang rasa sebagaimana Li Changgeng, si juru tangis itu?