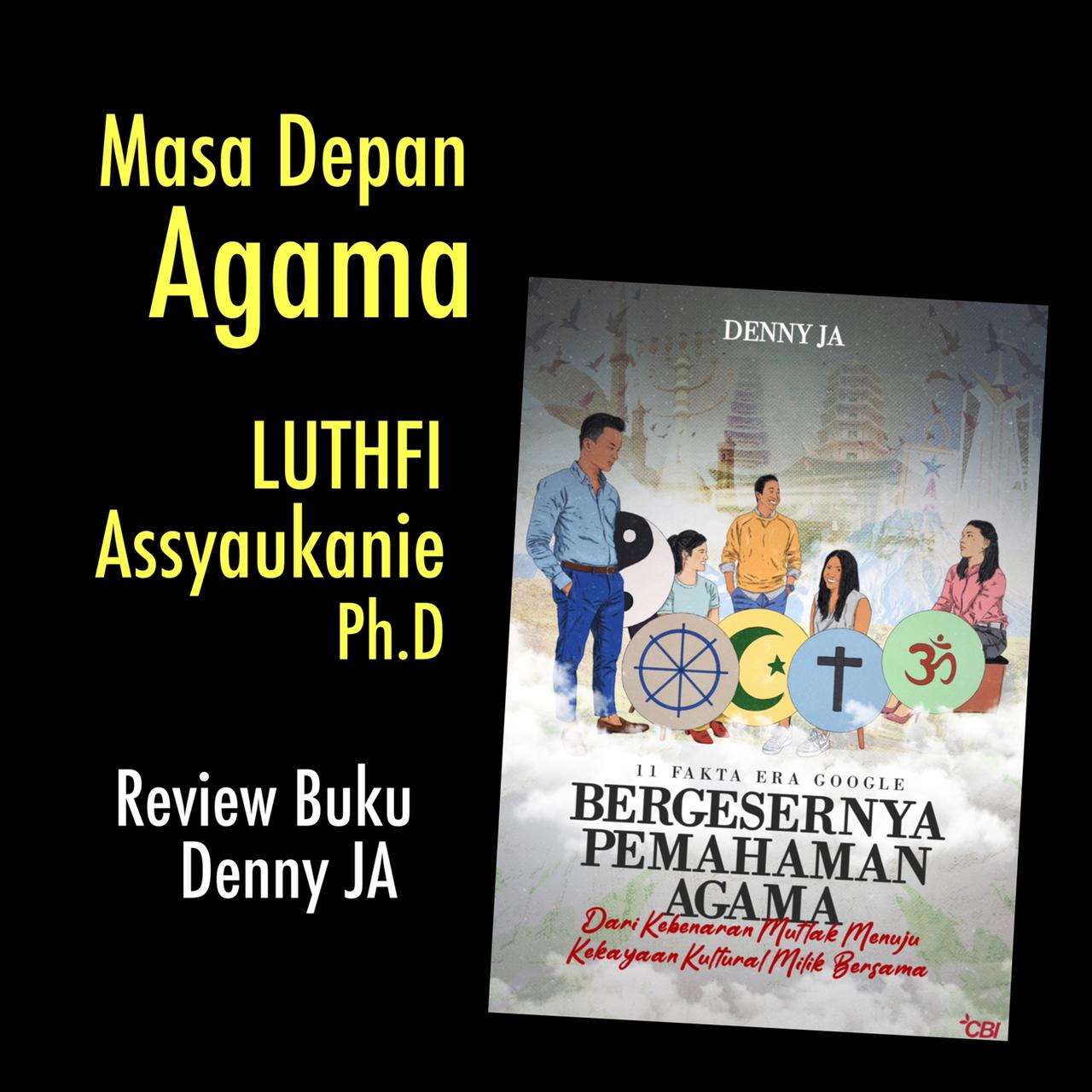Review Buku Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama, dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama, 2021)
Luthfi Assyaukanie
Buku terbaru Denny JA, 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama (2021), mengulas dua hal pokok.
Pertama, peran agama bagi kehidupan manusia modern. Kedua, temuan-temuan ilmiah yang bertentangan dengan beberapa doktrin agama.
Pada isu pertama, Denny JA menampilkan sejumlah data yang mengkontraskan pencapaian-pencapaian suatu negara dengan peran agama di dalamnya. Data-data itu diambil dari berbagai lembaga penelitian dunia, yang biasa melakukan riset tentang demokrasi, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan, dan beberapa isu lain.
Yang menarik dari data-data itu, semakin maju dan sejahtera suatu negara, semakin mereka tak memerlukan–atau tak menganggap penting—agama.
Denny memperlihatkan 10 negara paling bahagia sedunia, yang mayoritas warganya skeptis atau agnostik terhadap agama.
Sebagian besar mereka adalah negara-negara Skandinavia dan negara-negara Eropa. Sebaliknya, secara kontras, data-data itu menunjukkan, semakin terbelakang suatu negara, semakin mereka percaya pada agama.
Negara-negara yang berada di urutan bawah dalam hal kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebersihan, umumnya adalah negara-negara yang warganya sangat percaya pada agama.
India dan Indonesia adalah contoh negara yang tingkat kesejahteraan dan kebersihannya rendah, tapi memiliki kepercayaan pada agama yang sangat tinggi.
Pada isu kedua, Denny JA mengemukakan sejumlah pertanyaan kritis terkait doktrin dan keyakinan agama. Lalu, Denny mengkontraskannya dengan temuan-temuan ilmiah yang bertentangan dengan keyakinan itu.
Misalnya, tokoh Musa menurut temuan ilmiah hanyalah fiksi, banjir Nuh tak pernah terjadi, dan pusat penyebaran Islam adalah Petra di Yordania, bukan di Mekkah.
Saya ingin mengulas dua isu itu dengan perspektif yang agak berbeda dari cara pandang Denny.
Jika pada isu pertama Denny JA kelihatan cukup tegas dalam menyatakan bahwa agama memang tidak atau kurang memiliki relevansi bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, pada isu kedua, dia tampak “labil” dan memilih sikap “politically correct,” ketimbang mengambil sebuah posisi tegas sebagai konsekuensi dari data-data yang dimilikinya.
Berkali-kali Denny mengatakan bahwa agama masih tetap relevan dan berguna bagi kehidupan personal manusia. Untuk menguatkan sikapnya, dia bercerita pengalaman pribadinya dalam beragama, termasuk mengerjakan umrah sebanyak empat kali ke tanah suci Mekkah.
Agama dan Keterbelakangan
Sebagian besar negara yang mengalami defisit demokrasi, kebahagiaan, dan kesejahteraan adalah negara-negara muslim.
Pertanyaan yang harus diajukan adalah mengapa negara-negara muslim terbelakang atau tertinggal dari negara-negara lainnya?
Mengapa negara-negara Barat mengalami kemajuan yang luar biasa sementara kaum muslim mengalami kemunduran?
Semua pencapaian yang direkam dalam indeks pencapaian dunia, baik itu demokrasi, kesejahteraan, maupun kebahagiaan, terkait erat dengan pertanyaan ini.
Jadi, jika kita ingin tahu mengapa masyarakat maju menganggap agama tak penting sementara masyarakat terbelakang menganggap agama penting, kita harus menjawab dulu mengapa sebuah masyarakat menjadi terbelakang.
Karena keterbatasan ruang, saya ingin fokus pada masyarakat muslim saja. Saya ingin menjawab pertanyaan mengapa kaum muslim terbelakang?
Ada banyak studi yang mencoba menjelaskan mengapa kaum muslim mundur padahal mereka pernah mengalami kejayaan (abad ke-7 hingga ke-12).
Studi mutakhir dilakukan oleh Ahmet Kuru dalam bukunya, Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment (2019). Dalam buku yang banyak menyita perhatian akademis ini, Kuru menyimpulkan bahwa sebab utama kemunduran kaum muslim adalah akibat aliansi ulama dan negara.
Aliansi ini sudah ada sejak formasi kerajaan Islam, tapi semakin menguat sejak abad ke-11. Kuru berpandangan bahwa aliansi ulama-negara tak hanya melemahkan peran kelas menengah (borjuasi) yang sebelum abad ke-11 mendominasi struktur masyarakat muslim, tapi, aliansi itu juga memperkuat otoritarianisme negara.
Aliansi itu sendiri menguat karena desakan situasi yang dialami kekhalifahan Islam. Menjelang abad ke-10, kekhalifahan Islam tercerai-berai menjadi beberapa kerajaan besar dan kecil.
Ada Fatimiyah di Mesir dan Maroko, Idrisiyah di Maghribi, Buwayhid di Iran, Alawiyah di Irak, dan Karamitah di Yaman.
Pemberontakan di mana-mana dan sekte-sekte Islam non-Sunni mendirikan kerajaan mereka sendiri. Untuk mengatasi situasi itu, al-Qadir (947-1031), khalifah ke-25 Abbasiyah, meluncurkan program penangkalan dengan merekrut sejumlah ulama.
Para ulama ini dipekerjakan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diproduksi penguasa. Pada 1011, al-Qadir mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan “Manifesto Baghdad.”
Isinya, memerangi kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan dengan penguasa. Target utama dekrit ini adalah kaum Syiah, Mu’tazilah dan kelompok-kelompok Khawarij.
Para ulama memainkan peran besar dalam melancarkan kampanye pemberangusan dan penumpasan terhadap kelompok-kelompok non-Sunni itu.
Hanya dalam dua generasi, kampanye itu berhasil. Kerajaan-kerajaan Syiah satu-persatu tumbang dan kekuatan Sunni terkonsolidasi.
Untuk menyemai Doktrin Al-Qadir lebih dalam, penguasa Sunni membangun lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Sekolah Nizamiyah yang dibangun untuk menguatkan ortodoksi Sunni.
Berbeda dari sekolah-sekolah pra-abad ke-11, kurikulum Nizamiyah tidak memasukkan mata pelajaran umum. Sains, Kedokteran, dan Matematika dikeluarkan dari daftar pengajaran. Filsafat diajarkan bukan untuk mengembangkannya, tapi sebagai alat untuk menyerang para filsuf.
Sejak saat itu, menurut Kuru, kaum muslim mengalami kemunduran. Yang paling parah adalah kemunduran intelektual.
Terbukti, setelah kerajaan-kerajaan Islam meraih kejayaan militernya kembali (di bawah Ottoman, Safawiyah, dan Mughal), produksi pengetahuan mengalami kemunduran serius.
Dunia Islam tak lagi memproduksi sarjana-sarjana besar sekaliber al-Khawarizmi, Ibn Haytham, Abu Bakar Al-Razi, Al-Farabi, dan Ibn Sina.
Memasuki abad ke-15 Eropa menjalani renaissance dan memulai revolusi pengetahuan dan industri. Sementara, dunia Islam memasuki masa stagnasinya.
Masa kemandekan intelektual ini berujung pada kolonialisme. Pada abad ke-19 dan ke-20, hampir seluruh negara muslim berada di bawah kekuasaan penjajah Eropa.
Singkatnya, aliansi ulama-negara adalah penyebab dan biang keladi dari kemunduran kaum muslim. Meski saya memiliki sejumlah kritik terhadap Kuru (saya pernah menulis hal ini di Jalankaji.com), masuknya agama ke dalam negara (lewat ulama) adalah penyebab kemunduran kaum muslim.
Di mana-mana, agama adalah penyebab kemunduran. Selama masa kegelapan, kehidupan bangsa Eropa didikte oleh agama. Dan mereka bisa keluar dari kegelapan, salah satunya, adalah dengan melawan agama.
Selama ulama terus mendikte negara, tak mungkin suatu negara bisa maju. Karakter ulama adalah konservatif. Inti ajaran konservatisme adalah menghalangi perubahan.
Masa Depan Agama
Isu kedua, tentang relevansi agama. Apakah agama masih relevan buat manusia modern? Bagaimana masa depan agama?
Satu hal yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa agama merupakan ciptaan manusia.
Agama diciptakan sebagai bagian dari proses evolusi manusia yang panjang. Agama baru hadir di dunia ini sekitar 70 ribu tahun silam. Manusia modern (homo sapiens) sudah ada lebih dari 200 ribu tahun lalu.
Agama-agama utama yang kita kenal sekarang (Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Budha, dan agama-agama China) lebih baru lagi.
Semuanya baru muncul di era kultivasi setelah revolusi pertanian (agriculture revolution). Yahudi baru muncul pada abad ke-15 SM, Hindu abad ke-8 SM, Budha abad ke-5 SM, Kristen abad pertama, dan Islam abad ke-6.
Agama-agama Mesir Kuno dan Babilonia sudah muncul bahkan jauh lebih awal dari agama-agama “samawi” ini.
Mengapa agama muncul? Sebagai fenomena spiritual, agama muncul sebagai akibat dari revolusi kognisi pada manusia.
Para ilmuwan sepakat, revolusi kognisi ini terjadi antara 70 ribu hingga 75 ribu tahun silam. Yuval Noah Harari menyebut mutasi gen sebagai salah satu sebabnya (Sapiens, 2011).
Dengan struktur otak yang baru, manusia memiliki kemampuan melebihi rata-rata hewan lainnya. Salah satu kemampuan yang tak dimiliki hewan-hewan lain adalah imaginasi.
Manusia bisa mengimaginasikan apa saja, merangkai gambar dan bentuk dari pengalaman-pengalaman personalnya.
Mereka bisa membayangkan makhluk yang secara real tidak ada wujudnya: kuda terbang, gajah bertangan delapan, setan, iblis, memedi, genderuwo, kuntilanak, malaikat, peri, tuhan, dan lain-lain.
Revolusi kognisi mendorong manusia menjadi makhluk yang kreatif. Mereka tak hanya mampu menaklukkan api dan membuat jarum, tapi juga pandai mereka makhluk-makhluk jejadian.
Agama sebagai fenomena spiritual mendapatkan peran fungsionalnya saat revolusi pertanian, ketika manusia memutuskan hidup menetap, setelah lebih dari 200 ribu tahun mengembara sebagai makhluk nomaden.
Dengan menetap, manusia memiliki waktu luang berlebih. Mereka tak perlu lagi berburu, karena makanan telah tersedia di lumbung-lumbung gandum dan ternak-ternak yang mereka domestikasi.
Yang perlu mereka pikirkan adalah bagaimana mengatur tetangga dan orang lain agar tidak saling mencuri. Dari sinilah muncul gagasan pemerintahan dan agama.
Pemerintah sebagai pengatur dan agama sebagai aturannya. Agama-agama yang kita kenal sekarang adalah produk revolusi pertanian.
Fungsinya sama seperti negara: mengatur manusia agar tidak saling menyerobot, mencuri, atau membunuh.
Pertanyaan apakah agama masih relavan sangat terkait dengan dua fungsi agama di atas.
Sebagai fenomena spiritual, agama terus tumbuh. Kemampuan imajinasi manusia tak terbatas. Mereka menciptakan dunia khayali yang sangat beragam.
Setiap agama memiliki anak kandung hasil dari imaginasi-imaginasi liar pendirinya. Yahudi melahirkan Kristen. Keduanya melahirkan Islam.
Hindu melahirkan Budha. Islam melahirkan Sunni dan Syiah. Sunni melahirkan Ahmadiyah. Syiah melahirkan Druz.
Di dunia Kristen, jumlah anak-anaknya (berupa sekte dan denominasi) tak terhitung jumlahnya.
Setiap ada penyendiri mengaku mendapatkan wahyu, sebuah agama baru bakal muncul. Hampir semua pendiri agama pada mulanya dianggap gila.
Nasib mereka ditentukan oleh seberapa banyak mereka mampu merekrut pengikut. Jika gagal, mereka akan dianggap pendusta. Jika sukses, mereka akan dianggap nabi.
Sebagai institusi, agama lambat-laun kehilangan relevansinya.
Hanya sedikit negara di dunia ini yang mengadopsi agama sebagai “panduan” bagi kehidupan mereka, seperti terjadi pada zaman axial dan abad pertengahan.
Sebagian besar negara sekarang ini membuat sendiri aturan pemerintahan yang umumnya bersifat sekuler.
Semakin sekuler sebuah pemerintahan, semakin besar potensinya untuk berkembang. Semakin religius sebuah pemerintahan, semakin besar peluangnya untuk terbelakang.
Demokrasi dan kebebasan akan berkembang dengan baik pada pemerintahan yang sekuler, yang jauh dari intervensi agama. Dengan kata lain, sebagai institusi, agama semakin tidak relevan buat kehidupan manusia modern.
Lalu, bagaimana masa depan agama? Denny JA menulis bahwa agama memiliki seribu nyawa. Artinya, agama tak akan pernah mati.
Dalam jangka pendek, tentu agama tak bakal mati. Dalam jangka panjang, agama dalam pengertian seperti yang kita pahami hari ini, pasti akan punah.
Daniel Dennet, seorang filsuf dan aktivis gerakan Ateisme Baru, meramalkan bahwa agama akan bertahan 500 tahun lagi.
Setelah itu, seiring dengan berubahnya peradaban manusia, berubah pula cara manusia memaknai kehidupan mereka.
Saya sepakat dengan Dennet. Tapi, tidak sepakat soal angka. 500 tahun terlalu lama. Jika kecerdasan umum buatan (artificial general intelligent – AGI) terealisasi sebelum 2050 dan manusia bisa berintegrasi dengan mesin-mesin cerdas itu, lambat-laun agama akan mati.
Ketika semua hal bisa diatasi manusia, termasuk mengunggah nyawa (mind uploading), ketika itulah kebutuhan terhadap agama sirna.
Pada momen itu, kata Harari, manusia tak lagi memerlukan tuhan, karena mereka telah menjadi tuhan (homo deus).
Dengan mempertimbangkan Hukum Moore dan melihat perkembangan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir, saya meyakini, agama akan mati dalam 100–atau paling lambat 150–tahun lagi.**
Luthfi Assyaukanie. Menyelesaikan PhD-nya dalam bidang sejarah politik di Universitas Melbourne, Australia.
Selain mengajar di Universitas Paramadina, Jakarta, Luthfi melakukan riset di sejumlah lembaga penelitian.
Pada 2020, bersama beberapa teman dekatnya, dia mendirikan ForSains, sebuah forum untuk mendiskusikan isu-isu sains dan perubahan.
-000-