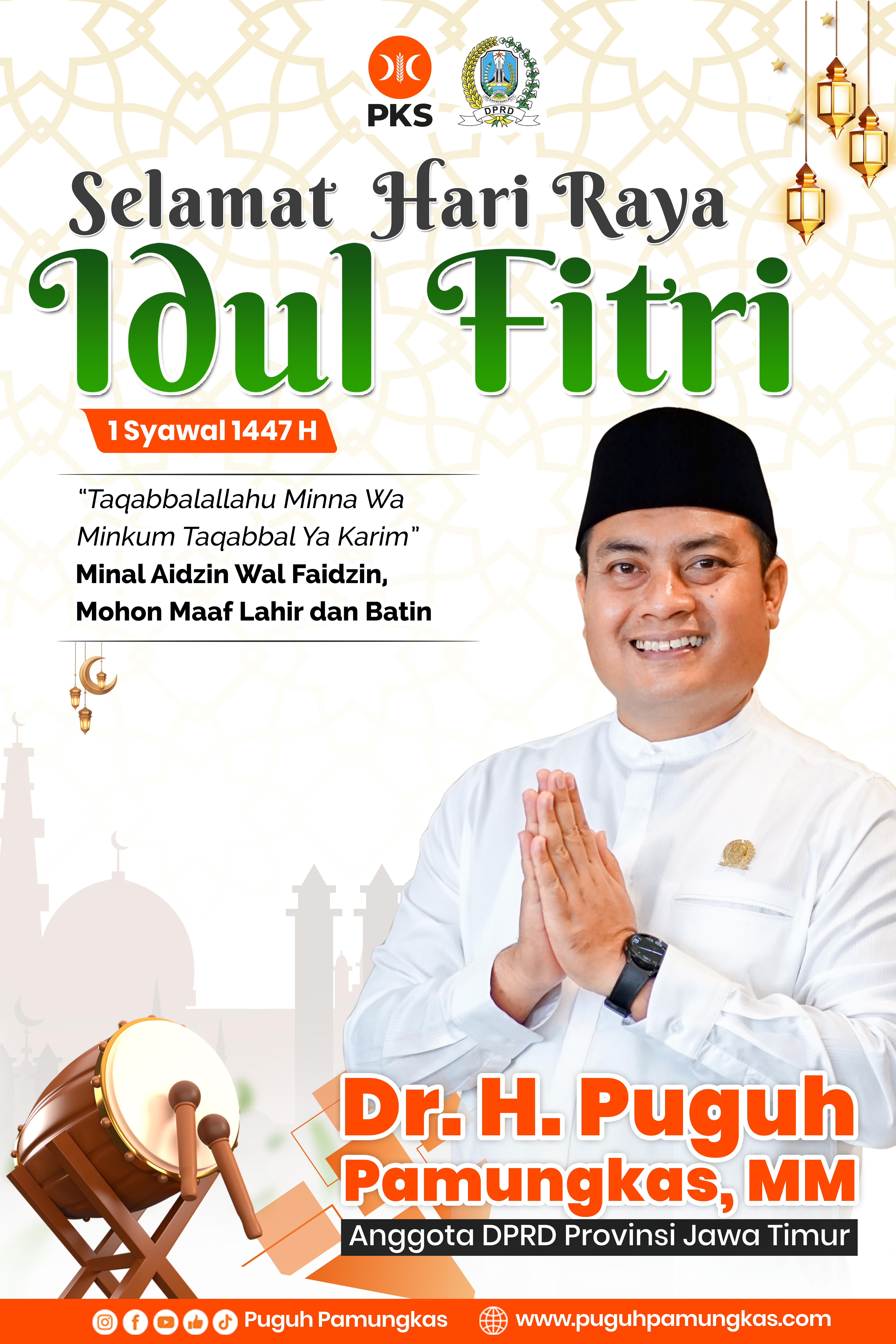Rekonsiliasi Budaya Sunda-Jawa di Surabaya yang dihadiri Gubernur Jbawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tuan rumah Gubernur Jawa Timur Soekarwo memunculkan wacana penggantian nama jalan di Jawa Timur.
Soekarwo memilih dua nama jalan di Surabaya, Dinoyo dan Gunungsari diganti menjadi Jalan Pasundan dan Prabu Siliwangi. Sementara Ahmad Heryawan mengatakan akan sesegera mungkin memberikan nama Majapahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada sebagai nama jalan di Jawa Barat.
Kedua kepala daerah tersebut berkeinginan menghapus “kesalahpahaman” suku Sunda dengan suku Jawa yang bermula dari peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357.
Umumnya sejarah Perang Bubat yang diungkapkan dalam bentuk novel atau prosa liris hampir sama, yakni menceritakan tentang gagalnya pernikahan Dyah Pitaloka (Citraresmi) dengan Hayam Wuruk akibat pengkhianatan Mahapatih Gajah Mada. Tokoh Gajah Mada menjadi sosok yang dibenci orang Sunda karena dianggap berkhianat kepada rajanya, Prabu Hayam Wuruk.
Dengan tipu daya untuk menyulut amarah Prabu Linggabuana, Gajah Mada meminta agar Dyah Pitaloka yang tadinya akan dijadikan permaisuri Hayam Wuruk, agar diserahkan sebagai upeti. Gajah Mada yang mengobarkan api peperangan, ketika hati Maharaja Linggabuana (ayah Pitaloka) terluka, merasa dihina dan direndahkan, lalu memilih untuk melawan karena tidak mau menyerahkan putrinya sebagai upeti.
Peperangan yang tak seimbang itu tentu saja lebih merupakan sebuah pembantaian. Maharaja Linggabuana, permaisuri, dan pasukan pengawalnya gugur di Bubat. Sementara Pitaloka memilih bunuh diri demi harga diri. Satu-satunya pengawal yang berhasil lolos adalah Pitar. Kisah tragis itu membuat banyak orang Sunda yang sakit hati dan perasaan itu tetap terpelihara hingga sekarang.
Benarkah Perang Bubat terjadi? Tidak ada satupun prasasti maupun literasi yang menceritakan terjadinya kejadian tersebut.
Mulai Kitab Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca dengan tarikh 1357 Masehi, Babad Tanah Jawi yang pertama ditulis oleh Carik Braja atas perintah Pakubuwono III tahun 1788 Masehi dan Babad Tanah Jawi kedua yang ditulis Pangeran Adilangu II dengan naskah tertua bertahun 1722 Masehi, hingga Buku History of Java tulisan Thomas Stamford Raffles seorang mantan Letnan Gubernur Pulau Jawa dan sekitarnya dan anggota masyarakat Asia di Kalkuta India yang diterbitkan tahun 1817, tidak ada satupun yang mengisahkan terjadinya Perang Bubat.
Peristiwa tersebut banyak dikutip dari Serat Pararaton dan Kidung Sunda (Sundayana). Siapakah penulis dari kedua kitab tersebut? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawabnya dan tidak ada yang menemukan naskah aslinya. Kisah tersebut diterjemahkan dan dipublikasikan oleh sejarawan di masa pendudukan Belanda.
Serat Pararaton merupakan kitab Sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi setebal 32 halaman seukuran kertas F4 yang terdiri dari 1.126 baris tanpa menyebutkan siapa penulis aslinya. Serat Pararaton diterjemahkan oleh Prof Dr. J.L.A Brandes pada tahun 1897 dalam sebuah bukunya yang berjudul Pararaton (Ken Arok) of het book der Koningen van Tumapêl en van Majapahit.
Kidung Sunda ditemukan sejarawan Belanda Prof Dr. C.C. Berg pada awal tahun 1920-an yang kemudian dijadikan buku berjudul Kidung Sunda, Inleiding, tekst, vertaling en aanteekeningen (1927) dan Inleiding tot de studie van het Oud-Javaansch (Kidung Sundayana) (1928).
Dalam Kidung Sunda versi asli yang terdiri dari tiga pupuh, tidak disebutkan siapa nama raja, ratu, dan putri asal Sunda tersebut. Nama Raja Linggabuana dan Dyah Pitaloka disebut karena kemiripan tahun penulisan Kidung Sunda dengan masa pemerintahan Raja Linggabuana pada tahun 1300-an. Bahkan sampai sekarang masih terjadi perdebatan di mana sebenarnya lokasi Bubat yang menjadi locus delicti Perang Bubat itu sendiri. Ada yang mengatakan di Babat (salah satu kecamatan di Lamongan, Jawa Timur), ada pula yang menyebut Bubat merupakan nama suatu wilayah di kawasan Tuban, Jawa Timur.
Mitos dan Devide et Impera
Ronald Barthes dalam bukunya Mythologies (1957) menyebut mitos merupakan bagian penting dari ideologi. Mitos versi Barthes ini berbeda dengan mitologi Yunani tentang dewa-dewa. Menurut Barthes, mitos masa kini bukan merupakan konsep, mitos tidak berisi ide-ide atau menunjukkan objek, mitos masa kini mengandung pesan-pesan. Dipandang dari segi struktur, mitos adalah bagian dari parole, sama seperti teks, mitos harus dilihat secara menyeluruh.
Dalam pandangan Barthes, mitos menjadi unsur penting yang dapat mengubah sesuatu yang kultural atau historis menjadi alamiah dan mudah dimengerti. Mitos bermula dari konotasi yang telah menetap di masyarakat sehingga pesan yang didapat dari mitos tersebut sudah tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat.
Penjelasan Barthes mengenai mitos tidak lepas dari penjelasan Saussure mengenai signifiant dan signifié, bahwa ekspresi dapat berkembang membentuk tanda baru dan membentuk persamaan makna.
Sebuah mitos dapat menjadi sebuah ideologi atau sebuah paradigma ketika sudah berakar lama, digunakan sebagai acuan hidup dan menyentuh ranah norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan mengapa mitos merupakan bagian penting dari ideologi. (Benny Hoed dalam Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya, 2011)
Mitos Perang Bubat menghasilkan “perseteruan” antara Suku Sunda dengan Suku Jawa hingga begitu dendamnya masyarakat Sunda terhadap suku Jawa, akibat mitos perlakuan yang tidak menyenangkan dari petinggi Kerajaan Majapahit kala itu, sampai-sampai di seluruh wilayah Tanah Pasundan seolah-olah “diharamkan” mengabadikan nama Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Majapahit.
Mitos yang sengaja “diciptakan” inilah yang dipergunakan penjajah Belanda untuk memecah Suku Sunda dan Suku Jawa untuk mempermudah menguasai. Mitos Perang Bubat dijadikan sebagai alat politik pecah belah (devide et impera). Mengapa Perang Bubat disebut mitos? Karena tidak ada satupun fakta otentik berupa prasasti atau literasi yang mengisahkan kejadian tersebut.
Belanda (melalui sejarawannya) rupanya sengaja menciptakan konflik baru antara Suku Sunda dan Suku Jawa. Sebagaimana dikatakan Randal Collins, manusia dipandang memiliki sifat sosial (sociable) tetapi juga mudah berkonflik dalam hubungan sosial. Konflik terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan. (Sutinah dalam Memahami Teori Sosial, 2018).
Dikutip dari laman wikipedia, politik devide et impera merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.
Mitos Perang Bubat seharusnya tidak menjadi sesuatu yang harus dibesar-besarkan yang bahkan masih bertahan sampai saat ini. Justifikasi sejarah terhadap peristiwa tersebut belum pernah ada yang meyakinkan secara faktual. Bisa saja Perang Bubat memang terjadi dan tercatat dalam sejumlah prasasti yang kini raib.
Mungkin kita perlu mencari prasasti-prasasti tersebut ke India karena seperti kita tahu, saat Raffles berkuasa di Jawa, ia gemar “mencuri” arca dan prasasti bersejarah bangsa untuk dipindahkan ke Kalkuta. Bisa juga terjadi Mpu Prapanca sengaja tidak menuliskan kisah Perang Bubat karena mendapat perintah raja yang berkuasa saat itu dan menilai Perang Bubat sebagai aib Majapahit sebagaimana Raja Louis XVI yang tidak pernah menuliskan kejadian terbakarnya penjara Bastille pada 13 Juli 1789 yang menjadi tonggak dimulainya Revolusi Perancis ke dalam buku diarynya
Jadi, masih layak kah seorang kepala daerah menyebut rekonsiliasi budaya akibat Perang Bubat sebagai alasan untuk mengubah nama jalan di wilayah yang dipimpinnya?
Rossi Rahardjo
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial
Universitas Airlangga Surabaya
Ketua Bidang Penyehatan Perusahaan SMSI Jawa Timur
Pemimpin Redaksi Harian Pagi Kabar Madura