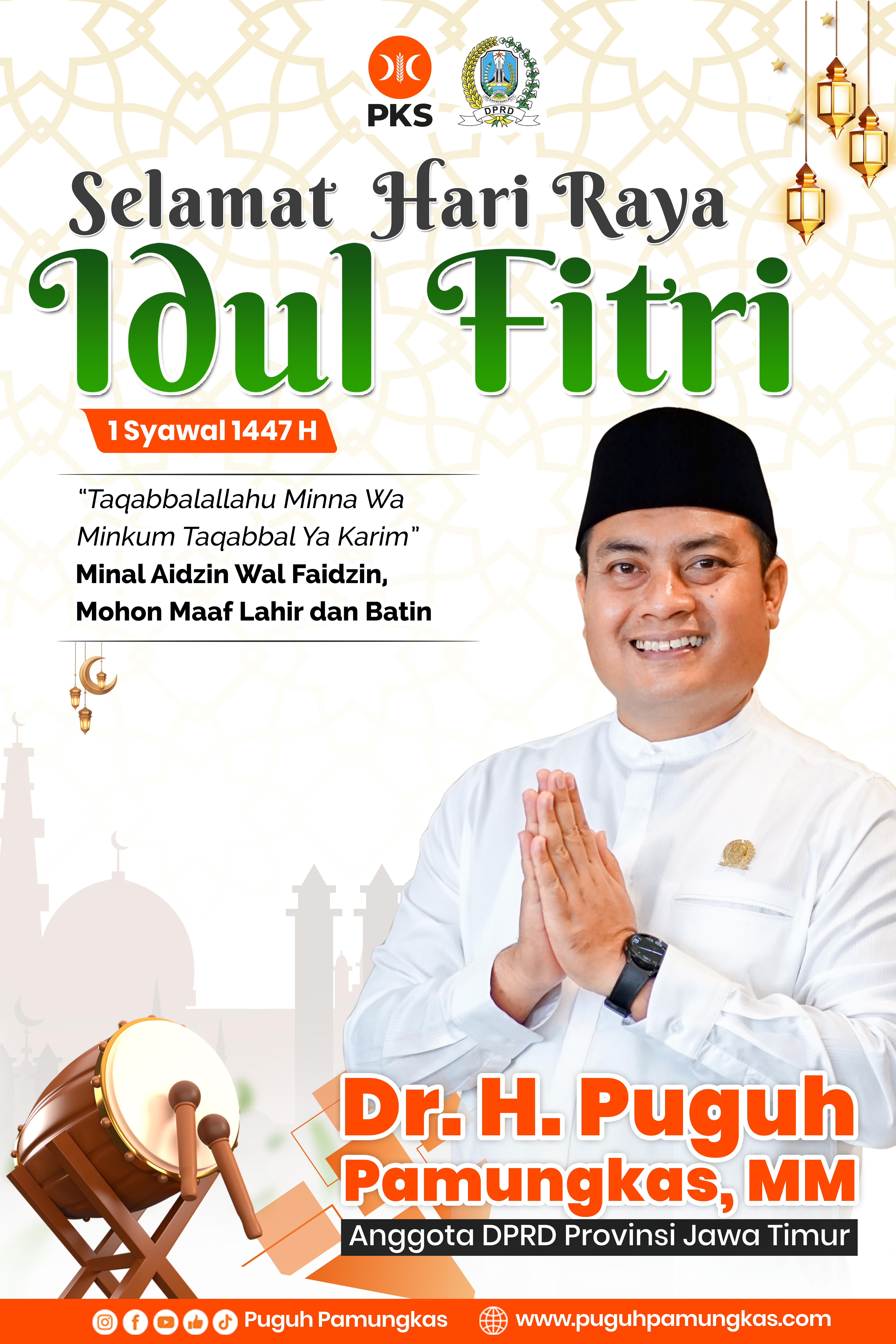Oleh : H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim PA Lumajang Kelas IA)
Undang-Undang Perkawinan ( UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) mengenal beberapa asas. Salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut adalah “asas mepersulit terjadinya perceraian”. Dengan kata lain, UU Perkawinan memang mengamanatkan kepada penegak hukum yang mempunyai kewenangan, agar berusaha secara sungguh-sungguh, mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena, bagi orang Islam institusi penegak hukum yang diberi kewenangan adalah pengadilan agama, maka pengadilan ini pulalah yang berkewajiban mengambil peran ‘membolehkan’ atau ‘melarang’ seseorang bercerai.
Secara tersirat upaya meminimalisasi perceraian sebenarnya juga telah ditunjang oleh sejumlah aturan lain, seperti Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Perma yang menjadi penyempurna sejumlah perma sebelumnya ini dengan tegas mewajibkan sejumlah perkara, terlebih dahulu harus menempuh mediasi. Sejumlah jenis perkara itu, termasuk di dalamnya perkara perceraian. Mediasi yang diatur oleh perma tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mengintegrasikan kewajiban upaya damai yang termuat dalam Pasal 130 HIR yang selama ini dianggap terlalu sumir dan beberapa tahun lalu menjadi pemicu kronis menggunungnya tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Pada saat yang sama dalam kesempatan bimbingan teknis, para petinggi Mahkamah Agung juga sering merespon tingginya angka perceraian tersebut. Dari evaluasi berkas yang ada, diperoleh kesan bahwa para hakim sangat gampang mengabulkan gugatan percaraian. Sehingga, suka atau tidak suka karena tupoksi tersebut, Pengadilan Agama harus mendapat label sebagai “kantor perceraian”. Bahkan, yang lebih mengenaskan label tersebut harus pula berimbas kepada institusi hakim. Hakim Agama mendapat predikat “hakim (tukang) cerai”. Stigma tersebut tentu tidak sepenuhnya salah. Realitas memang menunjukkan, bahwa hampir 80 persen dari jumlah perkara yang ada, memang didominasi perkara perceraian ( cerai gugat dan cerai talak ).
Hakim Pengadilan Agama adalah manusia juga. Sebagai manusia dia terikat dengan hukum-hukum kemanusiaan seperti manusia lainnya, seperti senang dan sedih. Ketika di hadapannya melihat 2 orang manusia yang sedang berseteru empati sang hakim akan terketuk dan bertanya, andaikan apa yang terjadi di hadapannya menimpa keluarganya. Apalagi, bila melihat pasangan suami istri yang berseteru hebat itu harus menyertakan anak-anak. Anak-anak yang polos dan tidak berdosa yang sesekali diajak menghadiri sidang itu, pasti tidak pernah membayangkan ketidakmenentuan masa depannya, akibat karamnya bahtera rumah tangga kedua orang tuanya. Hati sang hakimpun sering membuncah menyaksikan adegan demikian di depan matanya. Sesekali sang hakim terkadang harus mengajukan pertanyaan dengan suara berat dan parau, akibat menahan rasa pilu sekalipun harus tetap berjuang membendung air mata yang sudah mengembung di kelopak mata, agar jangan sampai jatuh tertumpah demi “jaim” profesi. Tidak jarang kesan menghadapi ‘tragedi rumah tangga’ para pihak dengan aneka problema dalam sidang harus terbawa dalam pikiran sang hakim tidak hanya ketika pulang kantor, tetapi juga ketika menjalani hari-hari libur. Ketika pada saatnya harus menjatuhkan putusan hati hakim seperti harus diikat rapat-rapat agar jangan sampai lebur ikut terbawa oleh tragedi karamnya sebuah biduk rumah tangga dengan segala isinya.
Dari sekelumit ilustrasi tersebut hanya ingin dikatakan, bahwa pada pokoknya para hakim agama pada umumnya menginginkan agar sepasang suami istri tidak mudah cerai. Upaya damai oleh Hakim dalam setiap persidangan hanya dimaksudkan agar para pihak mengingat, bahwa sebuah pernikahan dengan segala keindahan yang dilalui dapat dikenang lagi dan bisa berfikir seribu kali untuk mengambil jalan keluar kemelut rumah tangga melalui pintu perceraian. Mengapa?
Perceraian di samping berdampak positif dan karenanya dibolehkan, juga berdampak negatif. Bagi masing-masing pihak dampak negatif itu, antara lain, karena harus kecewa akbibat mimpi indah yang ada sebelum perkawinan berlangsung dan di awal-awal usia perkawinan ternyata hampa belaka. Kekecewaan terhadap pasangan dan berujung perceraian sering menimbulkan sikap trauma untuk memilih pasangan berikutnya. Dampaknya bagi anak juga tidak kecil. Beberapa anak mungkin dapat bangkit setalah mengalami masa-masa sulit pascaperceraian kedua orang tuanya. Akan tetapi, beberapa anak, terutama bagi anak yang masih di bawah umur, mungkin masalah itu akan berkelanjutan seumur hidup mereka. Akbiat perceraian kedua orang tuanya, harus memgalami masalah kejiwaan secara sirius. Dampak-dampak tersebut sebagaiamana ditulis dalam id.theasiaparent.com ialah seperti malas belajar sehingga menyebabkan prestasi akademiknya menurun, hilangnya minat berinteraksi sosial, sensitif secara emosional, kesulitan beradaptasi terhadap perubahan. Anak tersebut dengan sejumlah masalahnya harus berkumpul dengan salah satu ayah atau ibunya yang juga bermasalah secara pribadi. Pada saat itulah akumulasi masalah berikutnya dimulai. Beberapa orang tua yang hidup secara singleparent memang ada yang tetap tegar (survive). Akan tetapi, terdapat pula yang kehidupannya harus semakin terpuruk. Akibat berikutnya, mereka harus terjerumus ke dunia hitam. Kasus pembunuhan seorang anak angkat oleh ibu angkat di Sukabumi (grid.id 25/09/19) adalah contoh akumulasi masalah pascaperceraian. Kita tentu tidak pernah membayangkan seorang ibu tega membunuh anak angkat perempuannya dan kemudian berhubungan intim dengan kedua anak kandungnya. Yang lebih membuat kita miris, menurut pengakuannya di depan penyidik, hubungan initim sedarah (inses) itu sudah dilakukan lebih kurang sejak 2 tahun sebelumnya. Padahal, kedua anak laki-laki kandungnya juga masih terbilang di bawah umur.
Seorang ibu di Texas bernama Ashley Auzenne (39) ditemukan tewas bersama ketiga anaknya Parrish (11) Eleanor Auzenne (9), dan Lincoln (7). Dia nekat mengahabisi ketiga anaknya dan kemudian bunuh diri setelah seminggu sebelumnya bercerai dari suaminya Murvin Auzenne Jr. Berita yang dimuat RAKYATKU.COM (02/11/19) itu ditulis dengan judul mencolok “Kecewa Diceraikan Suami, Ibu Cantik Ini Tembak Mati Tiga Anaknya Lalu Bunuh Diri”.
Para Hakim Pengadilan agama pada umumnya telah menyadari betul dampak positif dan negatif perceraian tersebut. Tetapi, dalam batas-batas tertentu hakim memang ‘harus’ tidak berdaya. Sebab, dalam konteks penanganan perkara perceraian, pertanyaan terakhir yang ada dalam nurani para hakim—tanpa melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi pemicu masalah dari masing-masing pihak, suami atau istri—adalah dengan situasi dan kondisi rumah tangga berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, masih pantaskah ikatan perkawinan dipertahankan, dan berikut patutkah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak pengaju perkara dikabulkan. Dalam rangka menilai patut atau tidak patut dikabulkan inilah pada umumnya, ketika melakukan pemeriksaan perkara perceraian ( apabila sama sama hadir ) para hakim memerlukan waktu yang relatif lama.
Dalam konteks demikian pula, penyelesaian sebuah sidang perceraian sepatutnya memang, tidak dibatasi waktu secara kaku. Keberhasilan penyelesaian perkara perceraian, selain perkara verstek, sejatinya tidak dapat diukur dari sedikit atau banyaknya kuantitas waktu. Akan tetapi, dari seberapa tergambar dalam berkas yang menggambarkan improvisasi hakim menegakkan asas mempersulit perceraian, sekalipun mungkin harus berlama-lama. Sekalipun akhirnya memutus cerai juga setidaknya hakim sudah mendayagunakan segenap kemampuanya menghambat laju perceraian. Akan tetapi, kini tampaknya sistem kurang memberikan toleransi demikian. Maafkan!