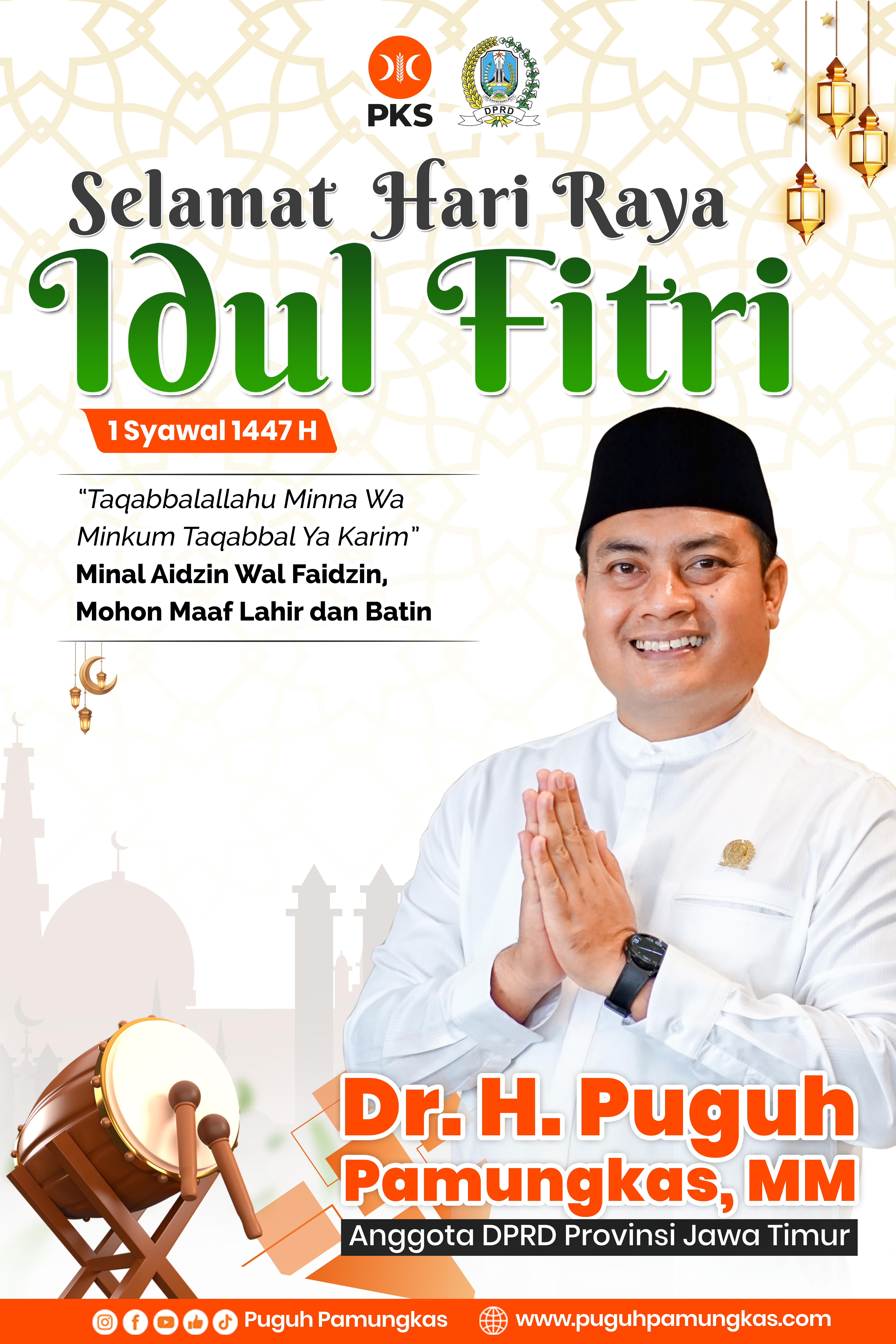Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Dalam atikelnya berjudul “Ramadhan Bulan Tirakat dan Berhemat”, Gus Maki pada intinya mengkritik perilaku kebanyakan umat Islam yang menjadikan bukan Ramadhan justru menjadi bulan boros. (Radar Banyuwangi, 24/03/2023). Bulan suci yang mestinya diisi dengan gairah ibadah yang semakin meningkat ini justru dipenuhi dengan sejumlah keinginan memenuhi nafsi kebutuhan yang justru tidak terjadi 11 bulan lainnya. Ketua Cabang NU Banyuwangi itu pun menunjuk sejumlah contoh, seperti kebiasaan membeli baju baru menjelang lebaran. Beliau pun mencontohkan kebiasaan lain dalam memenuhi hidangan buka. “Hal sederhana yang bisa kita perhatikan adalah ketika masuk waktu berbuka puasa. Aneka menu takjil buka puasa dihidangkan di meja makan. Mulai dari es teh, es jus, es buah, kolak, precet, kopyor, jenang, dan aneka menu makanan lainnya. Semuanya lengkap tersaji. Menu-menu yang tak pernah ada sebelumnya, tersaji lengkap ketika Ramadan tiba. Menu buka puasa seolah menjadi ajang aksi ”balas dendam” setelah seharian tidak makan dan tidak minum, menahan lapar dan dahaga. Seperti sedang terbebas dari kekangan, bisa makan dan minum sepuasnya ketika tiba waktu berbuka”, begitu katanya. Dengan retoris, pengasuh pesantren itu pun melanjutlkan: “Coba kita cermati dan perhatikan, pengeluaran kebutuhan hidup selama Ramadan bukannya berkurang, malahan menjadi lebih besar.”
Keprihatinan demikian jelas bukan tanpa alasan. Sebagai pemimpin umat beliau punya tanggung jawab moral mengajak umat kembali on the track. Di bulan ramadhan ini praktik kehidupan hedonis seolah mengalami klimaksnya. Padahal, esensi makna puasa adalah “menahan diri”. Euforia selama Ramadhan sering keluar dari yang seharusnya. Di suatu tempat sering terjadi, kesemarakan dan refleksi diri sebagai puncak penghambaan kepada Allah, hanya ditandai oleh lengkingan suara pengeras suara sampai larut malam. Itu pun hanya dilakukan oleh tidak lebih dari satu persen ummat yang ada. Selebihnya justru pada jam-jam ibadah, berbondong memadati mal-mal. Hampir semua toko mengalami peningkatan omset berlipat-lipat. Aktivitas umat bergaya hidup terjadi di luar nalar sehat. Sebagai contoh, sebulan sebelum ramadhan seorang telah memenuhi mal memburu diskon pakaian. Tetapi pada bulan ramadhan pun masih ikut-ikutan berdesak-desakan di kasir untuk membayar baju lebaran. Rumah yang yang ada pada bulan ramadhan pun harus tampil beda. Bank-bank juga secara massif menyediakan uang receh nan gres karena permintaan masyarakat. Pembagian angpao uang receh bukan sekedar sedekah biasa, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Yang pasti benar yang disampaikan Gus Maki, bahwa anggaran hidup di bulan ramadhan justru meningkat. Padahal, ramadhan mestinya medan untuk “bertirakat” dan “berhemat ria”.
Fenomena demikian tentu, perlu mendorong kita mengajukan sejumlah pertanyaan, mengapa hal ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab terjadinya fenomena demikian? Padahal, pada saat yang sama, di masjid dan musala ceramah, pengajian, atau pencerahan lain juga secara intens digalakkan. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, tuntutan pengeluaran demikian juga sering menimbulkan perselisihan rumah tangga. Dalam keluarga tertentu terjadi, suami yang tidak dapat memenuhi target-target anggaran Ramadhan dan lebaran sering menjadi bulan-bulanan istri. Terjadinya kenaikan angka krminalitas selama Ramadhan mungkin juga disebabkan oleh ironisme perilaku kita selama ramadhan yang demikian ini. Dan, yang pasti krimanalitas tersebut tidak ada hubungannya dengan hadits nabi tentang kondisi setan di bulan ramadhan yang menurut Rasulullah SAW dibelenggu oleh Allah SWT.
Syukurlah beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo, menghimbau agar tradisi buka bersama (bukber) oleh para pejabat ditiadakan. Himbauan demikian jika dipahami sekilas mungkin akan mamancing reaksi. Presidan tidak pro Islam, pemerintah anti syi’ar atau sejumlah stigma negatif lainnya. Akan tetapi, bagi yang tahu sebenarnya hal demikian juga dapat dipandang upaya mengurangi hidup hedonis. Coba lihat, berapa biaya yang harus digunakan untuk menyelenggarakan buka bersama, dari mana sumbernya dan siapa yang hadir di sana. Dalam logika brokrasi larangan tersebut jelas sangat rasional. Sebab, selama ini tidak pernah ada anggaran resmi untuk mengadakan buka bersama. Lantas dari mana sumber dananya? Pertanyaan demikian sering tidak bisa dijawab secara memuaskan oleh ‘panitia’.
Pada saat yang sama karena hanya alasan tren, setiap satker seolah wajib menyelenggarakan acara bukber. Dugaan pun muncul, bahwa ada potensi korupsi di acara bukber. Kita boleh berhitung, kalau hal ini terjadi di semua satker di seluruh republik ini, sudah berapa keuangan negara yang bocor hanya untuk acara bukber ini. Dan, itu digunakan untuk mengisi acara di bulan yang suci ini. “Wala talbisul haqqa bil batil”, begitu Allah telah jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Jangan-jangan KPK pun sudah melirik praktik-prakrik demikian. Dalam konteks demikian, itu larangan bukber bagi pejabat tentu tidak relevan dilawankan dengan konser dan keramaian lain yang diizinkan pemerintah.
Fenomena umat selama bulan puasa ini tampaknya memang bermuara pada satu titik puncak, lebaran. Lebaran yang semula sebagai hadiah besar “shoimain” dan “shoimat” berubah menjadi ajang adu gengsi. Fenomena mudik dari tempat yang jauh tidak sekedar sebagai ajang silaturahmi melainkan juga untuk ajang unjuk kebolehan atas capaian-capaian selama meninggalakan kampung halaman. Perilaku demikian jelas bertolak belakang dengan orang-orang yang telah mencapai puncak spiritualitas. Orang-orang demikian justru merasa sedih saat ramadhan berlalu. Mereka terus melakukan refleksi karena merasa belum berada pada posisi spiritualitas ideal sebanding dengan keagungan dan kesucian ramdhan sambil berandai-andai agar bulan-bulan lain berderajat laksana ramdahan. Lantas sudahkah kita termasuk kelompok demikian? Atau, ramadhan kita hanya akan menjadi rutunitas dengan sejumlah ironi yang berulang setiap tahun?