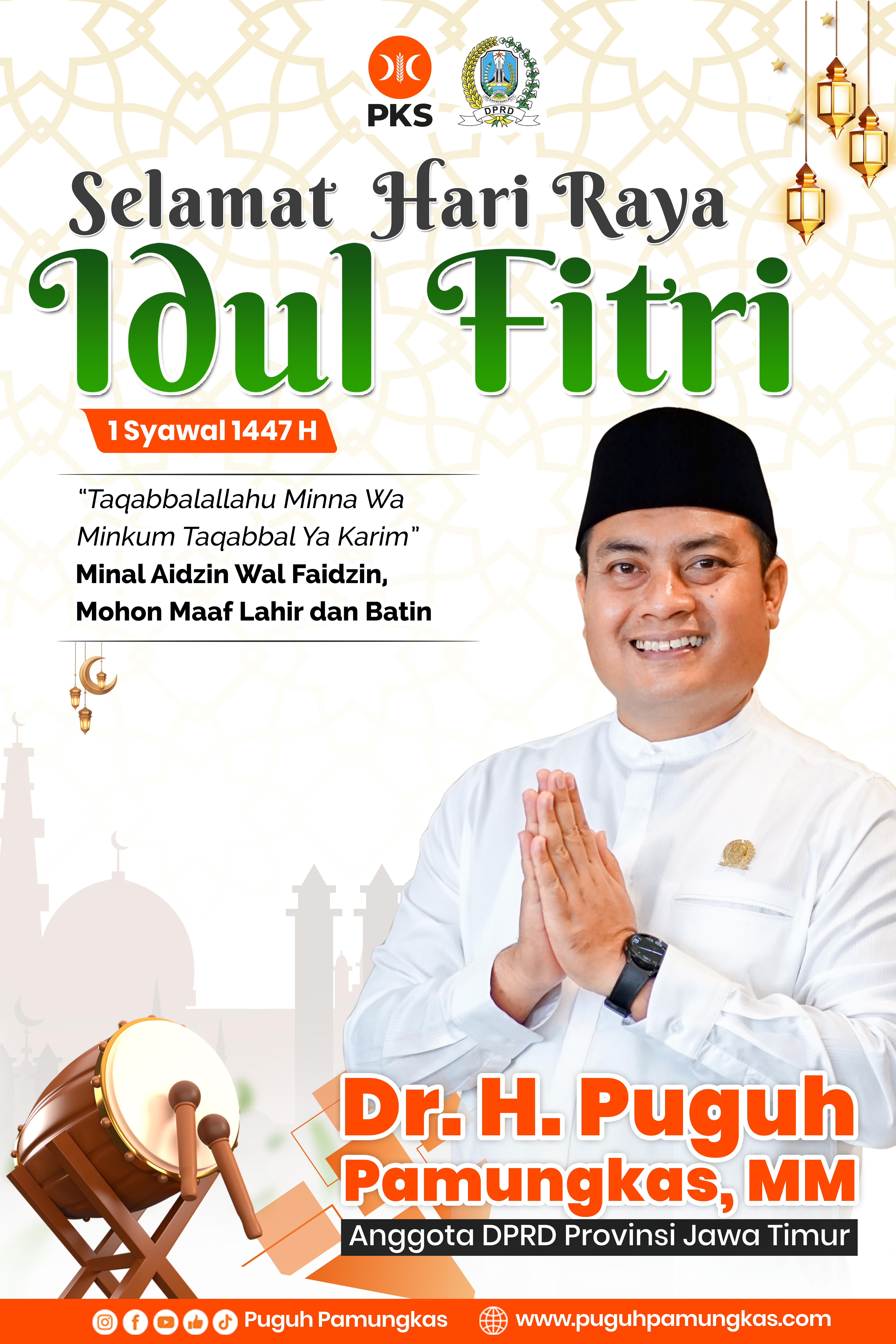Fatwa MUI
MUI itu kependekan dari Majelis Ulama Indonesia. Ulama oleh sebagian besar umat Islam didefinisikan sebagai pewaris Nabi. Ini bermuara dari hadits Nabi: “Ulama adalah pewaris para Nabi”. Jadi, singkatnya MUI itu adalah majelis para pewaris Nabi. Meskipun sebenarnya, tidak serta-merta mencerminkan sejarah para ‘pejuang’ di awal-awal penyebaran Islam di Indonesia, setidaknya di Pulau Jawa. Artinya, MUI tidak bisa disetarakan dengan Wali Songo, yang merupakan Dewan Penyebar Islam di Indonesia.
Tesis di atas merupakan awal ceramah Pak Sakerah dalam acara yang digagas Remaja Masjid. Jangan dibantah dulu, jika pean semua merasa tidak sependapat. Toh itu hanya pikiran seorang Sakerah, yang belum (atau memang tidak) layak menjadi ulama. Sebelum berangkat tour ziarah Wali Songo, Remaja Masjid itu mengundang Pak Sakerah. Lalu, tokoh fenomenal Madura ini melanjutkan ceramahnya:
Wali Songo itu sebuah dewan, namanya Dewan Wali. Anggotanya hanya sembilan orang. Jika ada anggota yang meninggal dunia, atau pulang kampung ke Champa atau Hadramut (Yaman), maka diadakan pergantian sehingga tetap sembilan orang. Dewan Wali tidak banyak melakukan rapat. Selama ratusan tahun—Dewan Wali berdiri pada abad ke-14–hanya tiga kali rapat. Dan itu pun mengganti anggota karena meninggal atau pulang kampung. Selebihnya, dalam rapat Dewan Wali itu, merevieuw program penyebaran Islam. Lalu, lebih banyak kerja menurut tugasnya masing-masing. Untuk menjadi Dewan Wali, tentu tidak perlu kampanye sana-sini, atau memajang gambar di pohon-pohon. Mereka lebih mengandalkan ‘bisikan’ Tuhan dari pada voting. Maka kata ‘mufakat’ lebih bermartabat dari pada gontok-gontokan di meja sidang.
“Berbeda dengan Dewan sekarang ya Bang?” Kamit menyela. “Lebih banyak rapat dari pada kerja. Dan tentu, lebih banyak mendapatkan thoyyiba halal dari pada angin bebas.”
“Lo,” heran Pak Komat. “Tugas utama Dewan memang rapat. Sebab, ia institusi legislasi. Ia digaji dari pundi-pundi anggaran negara. Jika tidak melakukan rapat, Dewan itu perlu studi banding. Kadang sampai Prancis segala. Makanya, ikamu perlu belajar tata negara,” katanya menunjuk Kamit.
Pak Sakerah membenarkan. Hanya saja, Dewan Wali bekerja bukan untuk melahirkan peraturan atau undang-undang baru. Tetapi lebih dari menyebarkan peraturan atau undang-undang milik Tuhan. Salah satunya, dengan memberi teladan. Jadi, meneladani Dewan Wali artinya sama dengan meneladani ulama. Pertanyaannya sekarang, apakah semua anggota Dewan itu bisa diteladani?
Menarik memang penjelasan Pak Sakerah di masa liburan ini. Pertama, banyak orang melakukan tour ziarah ke makam-makam wali. Kedua, berhubungan dengan fatwa MUI yang dianggap sebagai refsentatif dari ulama. Jadi, apa yang dikatakan Pak Sakerah ini layak didengar, jika perlu diikuti, meskipun belum layak disebut kiai apalagi ulama.
Untuk yang kedua, tentang Fatwa MUI, belakangan ini menjadi ‘sensasi’. Menurut Pak Sakerah, MUI akhir-akhir ini semakin ‘genit’. Jauh lebih genit dari pada Parpol. Meski MUI tidak berpolitik, tapi ‘gairah’ sosialnya, jauh melampui Parpol. Ujian kegenitan MUI bisa dilihat dari fatwa tentang Ahok. Dan sekali lagi, pendukung MUI jauh lebih banyak dari Parpol. Itu sih, pendukung setia, yang kepentingannya hanya satu: Islam. Fatwa terbaru adalah larangan penggunaan simbol-simbol non-Islami bagi umat Islam. Dan yang ini juga membuat Kapolri ‘kalang-kabut’. Presiden Jokowidodo perlu angkat suara. Dan tentu, Presiden merasa perlu memanggil Kapolri.
Masih belum setarakah MUI dengan Dewan Wali? Pertanyaan yang bermunculan di tengah ceramah Pak Sakerah.
MUI didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Pendirinya adalah para ulama di Indonesia: 26 ulama mewakili ulama dari 26 provinsi saat itu, 10 orang ulama unsur dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang cendekiawan muslim perorangan. Dibentuklah MUI.
Ketua MUI dari priode ke priode adalah Hamka dari Masyumi-Muhammadiyah, KH. Syukri Gazali dari NU, KH. Hasan Basri dari Masyumi-Muhammadiyah, KH. Muhammad Ali Yafie dari NU, KH. Sahal Mahfuz dari NU, KH Din Syamsudin dari Muhammadiyah, KH Ma’ruf Amin dari NU. Mereka tidak berebut atau saling klaim dukungan untuk jadi ketua. Artinya, jauh lebih martabat dari pada jabatan Dewan atau Majelis lainnya. Apalagi jabatan pimpinan Parpol.
Model dakwah Dewan Wali adalah budaya. Mengikuti sikon rakyat. Mereka damai dengan rakyat, sebab ia tidak serta-merta menentang kebiasaan rakyat. Maka tidak heran jika tembang, gamelan, dan klenengan, menjadi bagian penting dari media dakwah Dewan. Sebab, media itu sudah ada dan berkembang di tengah rakyat. Fatwanya, amar ma’ruf—dan dus nahi munkar tidak serta-merta diterapkan dengan kaku. Setidaknya, tidak seperti Ormas dengan mengatasnamakan agama, yang tiba-tiba melakukan sweping, melampaui tugas Polri. Ada siasat yang dibangun, dan salah satunya dengan kesenian. Di dalam kegiatan seni itulah, nahi munkar oleh Dewan Wali diselipkan.
Tentu, MUI tidak bisa seperti Dewan Wali. Suasananya beda. Maka, fatwa MUI tentang nahi munkar harus jelas. Memang menyakitkan. Tapi itulah majelis.
Fatwa memang tidak bisa dijadikan rujukan sebagai hukum positif. Dan memang bukan hukum positif. Hukum positif itu UU atau PP. Tapi umat Islam, semestinya merujuk pada Fatwa MUI, jika tidak sempat merujuk pada sumber aslinya, Alquran dan Hadits. Jika MUI dibilang ‘genit’, dan itulah kegenitannya, berani mengeluarkan fatwa haram dan halal. Meski kadang Pemerintah tidak sependapat, tapi kesigapan MUI dalam memahami masalah dan keadaan patut diacungi jempol. Sayangnya, MUI masih belum setara dengan Dewan Wali.
Pertanyaan sekarang, jika MUI tidak setara dengan Dewan Wali, barangkali masih ‘setara dengan majelis yang lain. Misalnya, MPR yang kependekan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Mungkinkah begitu? Untuk menjawab ini, Pak Sakerah perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Sebab, fatwa yang dikeluarkan kedua majelis itu berbeda. Wallahu a’lam.
Em Saidi Dahlan, 20122016