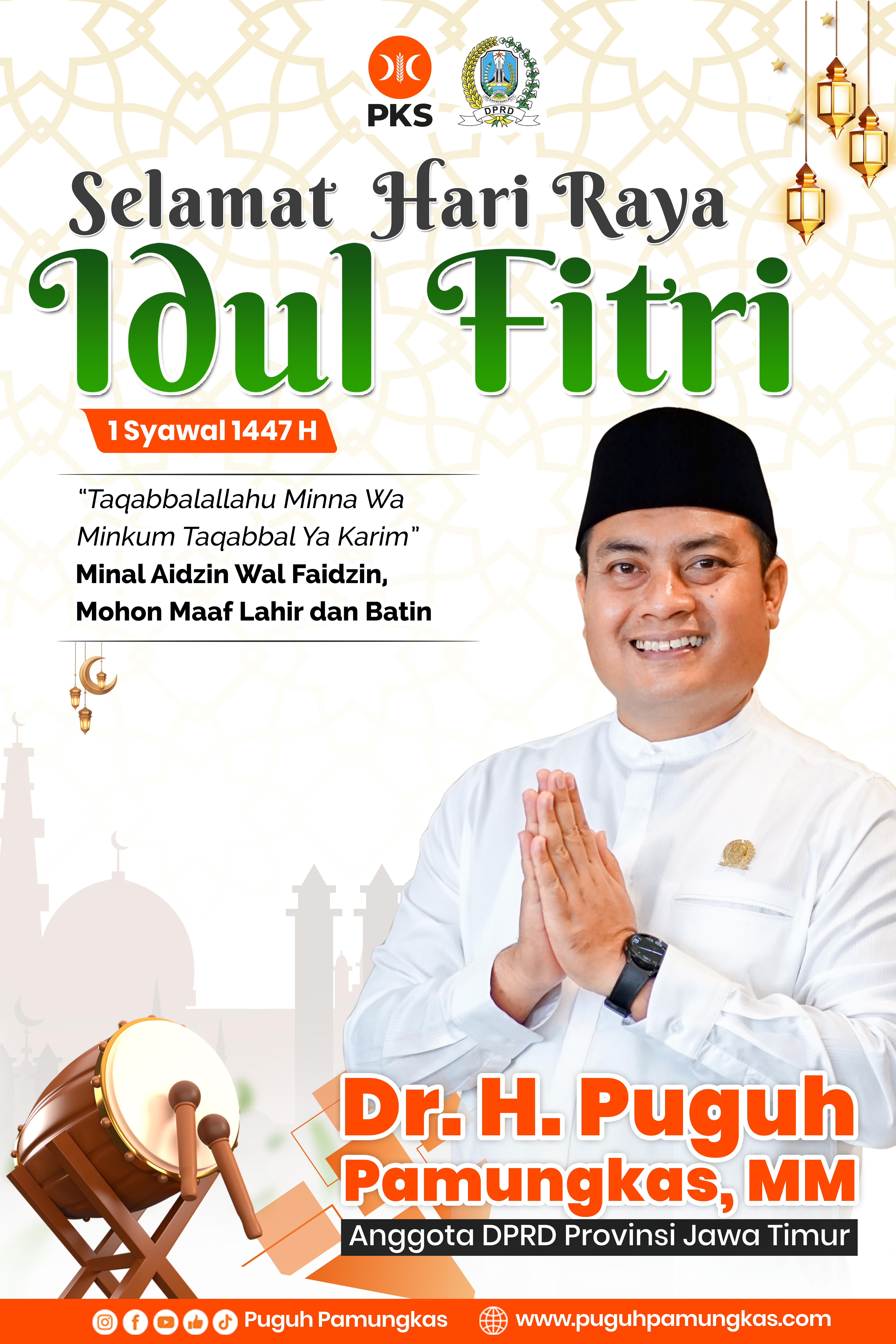Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim PTA Jayapura)
“Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Menag Bisa Ayomi Perbedaan Lebaran”. Judul berita yang ditulis portal CNN Indonesia (21/04/2023) ini tentu membuat kita lega. Pasalnya, sebelumnya ada sejumlah kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa pemerintah tidak netral dalam menyikapi lebaran ini. Kehawatiran ini timbul setelah ada sejumlah kepala daerah yang melarang penggunaan fasilitas umum untuk penyelenggaraan salat id. meskipun akhirnya mengenai hal ini telah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Beberapa kader dari kedua ormas terbesar itu juga sempat ‘bersiteragang’ via media yang membuat suasana menjelang babak akhir ramadhan sedikit menghangat.
Memang sudah lumrah polemik tentang tentang perbedaan hari raya idul fitri sering tidak bisa dihindarkan. Bahkan, polemik ini juga terjadi di tingkat ‘akar rumput’ dan menjadi bahan giunjingan saat bersilaturahmi lebaran. Beberapa kali lebaran sebelumnya memang tampak damai, khususnya antara penganut hisab hakiki “ansich” di satu pihak, dan penganut hisab plus rukyah di pihak lain. Kelompok pertama dengan ikon Muhammadiyah dan kelompok kedua dengan ikon NU. Kelompok pertama juga sering disebut sebagai pemegang teori “wujudul hilal”. Menurut teori ini meskipun bulan belum terlihat tetapi terdapat fakta bahwa bulan baru sudah muncul. Kemunculan bulan baru yang terjadi setelah ijtimak dalam siklus bulanannya ini menandakan permulaan bulan berikutnya atau tanggal satu. Sedang kelompok kedua penganut “teori hisab plus” pada ujungnya tetap berpegang rukyah. Kalau demikian masalahanya sampai kiamat kedua sistem tersebut memang tidak pernah berada dalam kutup yang sama. Sebab, ternyata masing-masing merasa mempunyai landasan naqli yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau pun kedua kelompok itu mengalami hari raya yang sama pasti hanya kebetulan saja dan tidak ada hubungannnya dengan konstelasi politik yang ada. Apalagi, dikaitkan dengan presiden tertentu.
Itulah sebabnya beberapa tahun lalu seorang pemikir Islam ( Agus Mustofa ) pernah menawarkan jalan komporomi. Kompromi tersebut ialah bahwa untuk tanggal satu dihitung tetap beradasarkan perhitungan hisab. Sebagai aktifitas astronomi tanggal tersebut adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa dibantah oleh siapa pun. Akan tetapi untuk memulai puasa atau hari raya kerena menyangkut ibadah, tetap tetap mengacu kepada keputusan pemerintah sebagai pemegang otoritas. Usulan ini tampaknya sangat realistis jika semua pihak berada pada semangat yang sama: mengakhiri perbedaan. Sayangnya, ‘usulan antik’ ini tidak pernah mendapatkan respon.
Satu hal yang pasti, dalam banyak hal Indonesia tampaknya memang berbeda dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara Islam sekalipun. Perbedaan hari raya yang biasa terjadi di samping perbedaan sistem, seperti penganut hisab hakiki ansih (Muhammadiyah) dan hisab hakiki dan rukyah (hisab plus, NU) juga disebabkan sistem politik yang ada. Di Indonesia, rupanya negara tidak diberi kewenangan penuh seperti negara Islam lainnya, untuk menentukan kapan hari raya. Konstitusi kita dengan tegas telah menjamin kebebasan penuh setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Bagi penganut agama penentuan kapan hari raya tampaknya merupakan bagian dari keyakinan. Negara hanya berkewajiban memberi ruang bukan memaksakan keyakinan.
Kalau sudah demikian, masalahnya memang bukan membuat keseragaman atas perbedaaan yang ada, melainkan bagaimana perbedaan tersebut agar menjadi budaya yang melembaga yang dapat dipahami semua pihak. Agar pemahaman perbedaan tersebut tidak sekedar basi-basi, masyarakat memang perlu diberi pencerahaan duduk persoalan sebenarnya. Seorang pakar hisab rakyat yang juga salah seorang pejabat Departemen Agama pusat (zaman Orba) ketika mendapat hujatan seputar sidang isbat, mengatakan, bahwa ketentuan penentuan hari raya memang bukan “produk ilmiah” tetapi “produk hukum”. Sebagai produk hukum, maka yang dikedepankan adalah rasa keadilan. Rasa keadilan ini, sebagai parameternya adalah suara mayoritas umat. Dan, yang pasti meskipun telah ditetapkan oleh negara via kemenag, dalam kasus hari raya ini, negara tidak pernah menjatuhkan sanksi pelanggarnya. Kaidah hukum: “keputusan negara merupakan keputusan final penghilang perbedaan” tampaknya tidak serta merta dapat diberlakukan pada kasus penentuan hari raya di Indonesia, seperti negara-negara Islam lainnya. Tentang apakah “sidang itsbat” sebagai aktivitas tahunan itu perlu dilestarikan atau dihilangkan saja seperti usulan beberapa pihak, tentu perlu kajian mendalam. Mengingat heteroginitas umat yang ada, suara berbagai ormas Islam perlu didengar. Yang demikian perlu agar negara tidak distigmatisasi melakukan “rejimisasi” ajaran agama seperti yang pernah dikemukakan beberapa tokoh kelompok tertentu baru-baru ini. Yang lebih penting, agar pemerintah siapapun juga tidak mencederai demokrasi dan konstitusi.
Pada akhirnya, semua pihak memang perlu menyadari, bahwa yang jauh lebih penting ialah agar ummat mengerti, bahwa dalam kasus idul fitri ini ada sesuatu “yang wajib” dan ada “yang sunat”. Yang wajib harus mendapat prioritas untuk dilaksanakan dan terus dijaga. Sedangkan yang sunat meskipun perlu dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaan tidak boleh mengganggu yang wajib. Yang wajib itu tidak lain ialah tetap menjaga ukhuwah dan yang sunat ialah merayakan idul fitri dan rangkaian ibadah yang menyertainya. Dalam ajaran Islam ketika harus memilih yang wajib dan yang sunat, tentu harus didahululan yang wajib. Akan tetapi sayang, kita sering gagal memilah dua persoalan tersebut. Akibatnya, idul fitri sebagai ajaran sunat, sering terasa lebih menggema melebihi yang wajib, yaitu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Selamat beridul fitri 1444 Hijriah.